
"Dan Kami hendak memberi karunia bagi orang-orang yang tertindas di bumi itu
dan hendak menjadikan mereka pemimpin
dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi."
(Al Qur’an, 28:5)
Pengantar
Pendekatan historis pada kajian agama, termasuk Islam, agaknya semakin mengedepan. Agama tak lagi sekadar dilihat pada dimensi seharusnya (das sein) melainkan lebih pada realitasnya, pada dimensi empiriknya yang bisa dilihat dan dirasakan (das solen). Dari model pembacaan yang historis seperti inilah kemudian sering muncul upaya-upaya untuk merefleksi kembali agama dalam kaitannya dengan realitas sosial. Adakah kaitannya agama – atau lebih tepatnya interpretasi terhadap agama – dengan struktur dan fenomena sosiologis masyarakat? Apakah benar untuk konteks umat Islam di Indonesia misalnya, kejumudan secara pemikiran, keterbelakangan secara material dan ketertindasan secara politis, banyak dipengaruhi oleh model beragama tertentu, seperti corak teologi Asy’ariah yang dinilai cenderung menggiring umat pada fatalisme dan kepasrahan terhadap takdir?
Berangkat dari refleksi semacam ini, banyak gagasan yang dilontarkan para cendekiawan kita. Harun Nasution misalnya, mengemukakan idenya tentang Teologi Rasional yang bisa dirujukkan pada ajaran Mu’tazilah. Nurcholis Madjid mengungkapkan gagasannya tentang “sekularisasi” dan “liberalisasi” pemikiran Islam. Sementara Abdurrahman Wahid, melampaui dua gagasan di atas yang dipandang masih terlampau teoritis, mengedepankan ide gerakan "sosio-kultural yang bermuara pada transformasi sosial umat Islam dalam konteks kehidupan berbangsa dan bermasyarakat”. Dalam bahasa lain, guna menyikapi fenomena ketidakadilan dan maraknya penindasan dalam kehidupan sosial, ia menekankankan pentingnya sebuah corak teologi yang berorientasi pada perubahan di tataran praksis, sebuah teologi transformatif.
Berkenaan dengan upaya menelusuri teologi transformatif ini, agaknya kita bisa menengok ke belahan selatan Benua Amerika yang didominasi kultur Katholik. Di sana muncul sebuah model beragama, lebih tepatnya model berteologi, yang dipandang baru sekaligus dinilai sangat relevan dengan kebutuhan umat manusia dewasa ini yang secara umum terbelit kemiskinan dan ketertindasan. Itulah Teologi Pembebasan. Teologi pembebasan bisa dikategorikan transformatif, karena ia menjembatani ‘iman’, sesuatu yang dipandang ‘berakar kepada langit’, dengan kebutuhan kongkrit kemanusiaan. Teologi ini tidak sekadar mengajak manusia untuk berteori tentang Tuhan dan keluhuran budi, tapi justru mengajak manusia menerjuni kenyataan sosial dan membuat perubahan di sana.
Untuk konteks Indonesia, pada tataran konseptual teologi pembebasan ini banyak diperkenalkan oleh F.X. Wahono Nitiprawiro, seorang pastor dari Ordo Jesuit. Dan akibat aktivitasnya yang dipandang sebagai salah satu bentuk advokasi ilmiah tersebut, Romo Wahono harus rela dicap sebagai ‘komunis’ dan mesti menyingkir ke luar negeri. Sementara, pada tataran praksis ide-ide teologi pembebasan ini banyak diterjemahkan oleh Romo Mangunwijaya yang terkenal dengan pembelaan dan pendampingannya terhadap ‘orang-orang kecil’ di bantaran Kali Code, Yogyakarta. Juga oleh Romo Sandyawan yang tenar ketika membantu Budiman Sujatmoko yang tengah dikejar-kejar penguasa pada saat transisi pemerintahan Orde Baru ke Orde Reformasi.
Mengingat coraknya yang transformatif, sekaligus dalam batas-batas tertentu terkesan mendobrak kebekuan, teologi pembebasan sangatlah menarik untuk dikupas lebih mendalam. Sekaligus diproyeksikan kedalam bingkai ajaran Islam dan realitas sosial masyarakat Indonesia. Adakah kita bisa mendapatkan manfaat dari teologi ini? Bisakah kita menemukan dimensi pembebasan dalam Islam? Benarkah kita memerlukan teologi pembebasan, atau lebih luasnya, model beragama yang membebaskan?
Beberapa hal tersebutlah yang ingin dicari jawabannya melalui tulisan ini.
Teologi Pembebasan: Pijar Kemanusiaan dari Amerika Latin
A. Akar Sosiologis dan Religius Teologi Pembebasan
Kemunculan Teologi Pembebasan banyak dikaitkan dengan pergerakan sosial dan intelektual di Amerika Latin hingga pertengahan abad 20. Ada beberapa hal yang ditengarai memicu kemunculan model teologi ini. F.X. Wahono, yang banyak merujuk pada tulisan Juan Luis Segundo, Erico Dussel dan Aloysius Pieris, menempatkan dinamika pergulatan kaum agamawan Khatolik dan institusi Gereja dalam menyikapi realitas sosial yang didominasi warna kemiskinan dan penindasan sebagai latar belakang utama kemunculan Teologi Pembebasan.
Dalam konteks perkembangan sejarah Amerika Latin, kaum agamawan Khatolik dan Gereja memang memiliki peran yang sangat signifikan. Keterlibatan mereka dalam derap perjalanan sejarah bangsa-bangsa Amerika Latin yang diwarnai fenomena kolonialisasi, penginjilan, pergantian kekuasaan, pertarungan antar kelas, sekaligus penindasan dan pertumpahan darah terbilang intens. Berawal dari perjalanan Columbus ke West Indies pada tahun 1492, kemudian dilanjutkan dengan penaklukan Hernan Cortez di wilayah Mexico dan Cuba sepanjang tahun 1500-an, kisah penginjilan dan dialektika relasi antara tokoh agama dan Gereja dengan para penguasa, menjadi bagian yang tak terpisahkan.
Saat itu, berkembang sistem patronato, dimana kepada para penguasa dilimpahkan kekuasaan untuk mewartakan iman sekaligus mengurusi masalah-masalah ekonomi dan politik di tanah-tanah jajahan. Dalam bingkai sistem ini, wajah tokoh agama dan gereja terasa menjadi gelap, karena dalam posisinya yang sub-ordinat, mereka seakan menjadi pembenar dan peneguh realitas kekerasan dan penindasan yang dilakukan para penguasa terhadap penduduk asli Benua Amerika, yaitu kaum Indian. Mereka bahkan turut melakukan kekerasan dalam bentuk yang lain. Dengan mengandaikan bangsa Indian seperti tabula rasa, mereka melakukan penginjilan dengan gencar, yang pada akhirnya mencabut bangsa Indian dari akar-akar kultural dan warisan kemanusiaan mereka sendiri.
Di tengah wajah gelap seperti itulah, muncul sisi yang lain. Ada pijar dari Gereja dan tokoh agama yang membawa harapan pada mereka yang tertindas. Bartolome de Las Casas, menjadi sosok yang paling berpengaruh untuk menggerakkan para pastor dan uskup menjadi “pelindung orang-orang Indian”. Ucapannya teramat terkenal dan dipandang sebagai cikal bakal praksis pembebasan:
“Tuhan berkenan memilih saya sebagai pelayan-Nya ... untuk mencoba mengangkat harkat Martabat hidup orang-orang yang sering kita sebut orang-orang Indian .... kepada tingkat kebebasan yang asali yang telah dirampas dengan tidak adil, dan untuk membebaskan mereka dari kematian sadis yang kerapkali dialami secara paksa.”
Demikianlah, pada masa-masa penaklukan bangsa-bangsa Eropa terhadap bangsa pribumi, kita melihat adanya dinamika internal di kalangan tokoh agama dan Gereja. Di satu sisi, ada pihak yang terkesan oportunis, memanfaatkan tangan-tangan kekuasaan untuk mencapai “tujuan-tujuan agama”. Sementara di sisi lain, justru menukik pada substansi agama dengan mengkritisi kecenderungan agama yang borientasi seperti penguasa: memperlebar wilayah kekuasaan, maupun memperbanyak jumlah pengikut.
Dinamika seperti ini berlanjut ke fase sejarah Amerika Latin selanjutnya. Tahun 1808-1852, berlangsung Revolusi Kemerdekaan yang dimotori kaum borjuis Kreole, para keturunan Spanyol di Amerika Latin. Gerakan ini menghantarkan golongan elit baru ke puncak kekuasaan. Sekalipun sistem kerajaan yang cenderung tiranik digantikan sistem perwalian demokrasi, pada realitasnya kekuatan politik hanya dikuasai 20 % populasi Amerika Latin pada saat itu, yaitu kaum kulit putih Kreole. Sementara 80 % sisanya terpinggirkan, termasuk diantaranya kaum mestizoz, Indian dan Negro.
Kaum Elit Kreole-lah yang kemudian mendominasi baik secara politis maupun ekonomis. Mereka memegang kukuh kekuasaan politis yang direbut dari Spanyol. Sementara kekuatan ekonomi mereka pupuk dari akumulasi keuntungan yang diperoleh lewat transaksi perdagangan dengan Inggris dan Amerika Utara.
Sebagaimana Gereja pernah memanfaatkan perlindungan penguasa Spanyol, pada fase ini mereka pun mencoba menjadi intim dengan penguasa Kreole, dengan kaum borjuis. Dan pada akhirnya, Gereja lebih banyak condong pada keputusan yang memihak kepentingan kaum elit itu ketimbang kepentingan rakyat kebanyakan.
Kemudian, semenjak tahun 1930-an saat Amerika Latin tenggelam dalam resesi ekonomi dan keguncangan sosial politik, kalangan militer mengambil alih kekuasaan dengan melakukan coup d’etat, yang seringkali diiringi pertumpahan darah. Pada titik inilah, praksis pembebasan kembali muncul. Kesadaran bahwa revolusi senjata selama perang kemerdekaan hanya melahirkan penjajah baru yang menyingkirkan rakyat jelata dalam lorong-lorong gelap sejarah, melahirkan kesadaran baru: masyarakat membutuhkan revolusi kebudayaan, yang akan menciptakan masyarakat awam yang militan.
Demikianlah, di Amerika Latin berkembang Aksi Katholik yang melibatkan massa dari berbagai kalangan dalam jumlah besar. Aksi yang merupakan wujud praksis pembebasan ini menjadi semacam pengimbang bagi kecenderungan sebagian elemen keagamaan yang mapan untuk tetap berada dalam kungkungan sistem patronato yang sedikit banyak memberikan keuntungan politis dan ekonomis.
Dan pada akhirnya, seiring dengan perlawanan terhadap kecenderungan oligarkis kalangan penguasa, militer dan pemilik modal (baik dari kalangan dalam negeri maupun dari negara-negara maju), dengan dimotori para tokoh seperti Gustavo Gutierrez dan Dom Helder Camarra, muncul gerakan pembebasan yang berangkat dari refleksi iman dalam bentuk yang lebih sistematis. Dalam bentuk Teologi Pembebasan.
Dari uraian yang agak panjang ini, kita bisa menangkap benang merah sejarah yang mendasari kemunculan Teologi Pembebasan. Pada dasarnya, corak teologi ini lahir dari pergulatan moral, intelektual dan sosial para agamawan dengan realitas kehidupan yang dihadapinya. Keprihatinan terhadap kemiskinan, penindasan dan ketidakadilan yang menjadi pengalaman empirik keseharian, menjadi pemicu sebuah upaya perumusan teologi yang bisa membebaskan manusia dari semua bentuk kegelapan kemanusiaan tersebut. Dan ini agaknya bisa dibandingkan dengan peranan kaum mullah dan cendekiawan di Iran, yang sepanjang sejarahnya hidup bersama dan menjadi pendamping rakyat yang tertindas oleh kekuasaan, hingga kemudian menelurkan Revolusi Iran pada tahun 1979.
Tapi sebenarnya, jika menengok pada analisis lain yang dikembangkan oleh Marian Hillar, kemunculan Teologi Pembebasan ini juga banyak dihubungan dengan upaya responsi Gereja dan kalangan Katholik terhadap perkembangan gerakan missionaris kaum Protestan, maraknya sekularisasi, dan penyebaran ide-ide komunisme. Tema-tema inilah yang menjadi pokok pembahasan dalam CELAM (Konferensi Uskup Amerika Latin) pada tahun 1955 di Rio de Jeneiro. Dari tulisan F.X. Wahono kita tahu bahwa pada konferensi ini jugalah muncul secara resmi ajakan untuk meninggalkan patronato; sebuah kecenderungan yang sedikit banyak menjadi salah satu fondasi praksis pembebasan. Dan pada konferensi itu, terekam bagaimana sengitnya uskup konservatif yang lebih suka bersekongkol dengan penguasa politik, dengan para uskup progresif yang ingin membuat “gereja mampu bergerak bebas di luar batas-batas politik, ekonomi dan budaya; tegar menjadi nabi zamannya”, yang dalam wujud praktisnya berbentuk kesediaan gereja untuk tidak berada dalam payung kekuasaan, melainkan hidup bersama mereka yang tak mempunyai kekuasaan, bersama orang-orang miskin, buruh dan petani yang tertindas.
B. Definisi, Metode dan Muatan Teologi Pembebasan
Phillip Berryman mendeskripsikan Teologi Pembebasan sebagai:
1. Sebuah interpretasi keyakinan Kristen mengenai penderitaan, perjuangan dan harapan kaum miskin.
2. Sebuah kritik dari masyarakat dan ideologi yang membenarkannya.
3. Sebuah kritik terhadap aktivitas Gereja dan orang-orang Kristen dari sudut pandang orang-orang miskin.
Dalam bahasa lain, Teologi Pembebasan secara sederhana dapat dipahami sebagai upaya penterjemahan Bible dan doktrin-doktrin kunci Kristen melalui pengalaman orang miskin. Teologi ini adalah teologi yang membantu orang-orang miskin menterjemahkan nasib mereka sendiri melalui cara yang baru.
Sementara dalam penelusuran yang lebih ketat mengenai definisi Teologi Pembebasan, kita bisa merujuk kepada paparan F.X. Wahono, yang mencoba terlebih dahulu memisahkan kata ‘Teologi’ dengan ‘Pembebasan’. Merujuk pada Segundo, teologi dimaknai secara dinamis sebagai “iman yang mencari pengetahuannya sendiri, untuk dapat mengarahkan praksis sejarah”. Rumusan ini dilengkapi dengan konsep dari Rubem Alves, “Teologi adalah ilmu pengetahuan bagi orang-orang yang kehilangan Taman Firdaus-nya atau belum mendapatkannya. Sebuah pencarian titik-titik acuan, cakrawala baru yang memungkinkan manusia menemukan arti hidup di tengah kekacauan yang membenamkan dirinya.”
Sementara istilah ‘pembebasan’, sejauh diungkapkan oleh para penggagas maupun pengamat Teologi Pembebasan seperti Guiterrez, Segundo Galilea, dan Ronaldo Munoz, dimaknai secara holistik sebagai:
1. Pembebasan dari belengu penindasan ekonomi, sosial dan politik, atau alienasi kultural, atau kemiskinan dan ketidakadilan.
2. Pembebasan dari kekerasan yang melembaga yang menghalangi terciptanya manusia baru dan digairahkannya solidaritas antar manusia, atau lingkaran setan kekerasan yang menantang orang untuk berperan serta dalam kematian Kristus, atau praktik-praktik yang menentang usaha pemanusiaan manusia sebagai tindakan pembebasan Tuhan.
3. Pembebasan dari dosa yang memungkinkan manusia masuk dalam persekutuan dengan Tuhan semua manusia, atau pembebasan spiritual menuju pemenuhan Kerajaan Allah, atau pembebasan mental, yakni penerjemahan dan penginkarnasian iman dan cinta dalam sejarah yang kongkrit yang ditandai oleh salib Kristus sebagai salib cinta yang mengalahkan kuasa dosa yang terjelma dalam situasi kekerasan.
Dengan demikian, istilah Teologi Pembebasan merujuk kepada satu upaya refleksi ajaran Kristiani yang dibenturkan dengan realitas sosial, dimana dari refleksi itu iman kemudian dimaknai tidak lagi hanya secara teoritis, tetapi justru dititikberatkan sebagai sebuah tindakan praksis. Seperti yang dirumuskan Hugo Assman, Teologi Pembebasan adalah “refleksi kritis atas proses sejarah pembebasan dalam arti iman yang muncul dari tindakan.”
Melihat corak teologi seperti ini, memang menarik untuk menelusuri akar-akar epistemologisnya. Ada banyak pandangan mengenai hal ini. Jika kita merujuk pada Ron Rhodes, disebutkan bahwa Teologi Pembebasan memiliki akar pada gagasan beberapa teolog Eropa. Setidaknya ada tiga orang yang bisa dikemukakan: Jurgen Moltmann, Johannes Baptist Metz, and Dietrich Bonhoeffer.
Moltman mengungkapkan pandangannya tentang kedatangan Kerajaan yang memberi Gereja visi transformasi masyarakat, sebagai lawan dari visi penyelamatan personal atau individual. Metz menekankan adanya dimensi politis pada iman, dan berdasarkan itu Gereja harus menjadi institusi kritisisme sosial. Sementara Bonhoeffer menggagas pentingnya mendefinisikan ulang agama dalam konteks sekuler. Teologinya menekankan tanggung jawab manusia terhadap sesama, dan penitikberatan pada nilai penglihatan dunia dengan ‘penglihatan dari bawah’ – yaitu dari perspektif dari kalangan miskin dan tertindas.
Selain akar teologi Eropa di atas, satu hal lain yang sering diungkapkan para pengamat adalah akar Marxisme. Kembali merujuk pada Ron Rhodes, Teologi Pembebasan memang menggunakan konsep Marxis sebagai instrumen analisis sosialnya. Dalam analisis Marx dikemukakan bahwa problema manusia merupakan hasil langsung dari eksploitasi kelas. Eksploitasi kelas ini sendiri muncul seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang menempatkan sekelompok orang yang menguasai sumber-sumber daya ekonomi (baca: pemilik modal atau kaum kapitalis) sebagai super-ordinat, dan kaum buruh atau pekerja sebagai sub-ordinat. Dalam konteks Teologi Pembebasan, model analisis seperti ini menjadi relevan untuk diterapkan karena ia berangkat atau didirikan di atas konfigurasi sosial Amerika Latin yang penuh warna penindasan.
Karena akar-akar seperti inilah kemudian muncul kritik terhadap Teologi Pembebasan, seperti bahwa ia sebenarnya tak lebih sebagai bagian dari Teologi Kerajaan Allah (yang banyak berkembang di Eropa Barat), atau teologi made in Germany, serta cenderung mencanangkan pertentangan kelas dengan mengabaikan penyelesaian kooperatif sebagai mana model analisis Marxis. Mengingat itu, menjadi penting untuk mendalami Teologi Pembebasan dari segi metode dan muatan, agar kita bisa memperoleh gambaran kebenaran kritik-kritik tersebut. Sekaligus untuk menguji pandangan di awal bahwa Teologi Pembebasan merupakan sesuatu yang baru, orisinil dan mendobrak.
Pada satu sisi, kita bisa mengungkapkan bahwa letak perbedaan mendasar antara Teologi Pembebasan dengan teologi Eropa Barat yang berakar pada metode transendental Immanuel Kant, adalah pada titik ‘praksis’ dan ‘teoritis’. Yang pertama dinisbatkan kepada Teologi Pembebasan, sementara yang kedua pada Teologi Eropa Barat. Jika metode transendental Kantian berusaha menjelaskan arti iman dalam pengertian iman, maka metode teologi pembebasan menegaskan bahwa ia bermaksud mentransformasi dunia sebagai realisasi iman yang hanya menjadi iman sejauh dilakukan dalam praksis pembebasan. Dengan kata lain, jika dalam metode transendental teologi merupakan sarana untuk meraih kepuasan budi, baru kemudian dari sana melakukan tindakan yang sesuai dengan iman yang telah lebih dimengerti itu, maka pada metode teologi pembebasan, teologi itu sendiri justru menjadi yang kedua sesudah langkah pertama berupa praksis pembebasan. Dan seperti yang dikatakan oleh Marian Hillar, lewat Teologi Pembebasan ini kaum agamawan lantas menjadi “intelektual organis” yang menjembatani kesenjangan yang tajam di dalam masyarakat Amerika Selatan.
Selanjutnya, sebuah diagram (Lingkaran Hermeneutika) yang dirumuskan oleh Segundo akan lebih membantu kita memahami secara teknis metode Teologi Pembebasan, sekaligus menjawab pertanyaan tentang sejauh mana pengaruh dan keidentikan Marxisme terhadapnya.
Keempat langkah dalam lingkaran hermeneutika tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
• Langkah pertama: Cara kita mengalami “realitas yang terumuskan” mendorong kita pada posisi “kesangsian ideologis”
• Langkah kedua: “Kesangsian ideologis” kita tadi, kini diterapkan terhadap superstruktur (besertanya juga teologi yang beku)”
• Lagkah ketiga: “Kini kita telah mendapatkan cara baru mengalami realitas teologis yang mendorong kita pada posisi “kesangsian eksegetis”, kita mulai menyangsikan bahwa “interpretasi kitab suci” yang ada telah tidak mengikutkan data yang penting.
• Langkah keempat: Kini kita telah memiliki hermeneutika baru, artinya kita sudah mempunyai “cara baru yang kaya dan mendalam dalam menginterpretasi Kitab Suci”. Dengan perolehan yang baru tersebut, kita “mengalami kembali realitas secara baru”.
Berdasarkan empat langkah inilah, kita bisa melihat perbedaan yang jelas dan mendasar antara Teologi Pembebasan dengan ideologi Marx. Adalah benar, bahwa Karl Marx berangkat dari penghayatan atas realitas, dengan merumuskan realitas sejarah sebagai perjuangan antar kelas. Lebih spesifik, realitas sejarah adalah perjuangan kaum proletariat untuk menumbangkan kekuasaan kaum borjuis. Dari penghayatan ini, ia kemudian beranjak pada kesangsian ideologis dengan menyatakan bahwa “Ideologi yang berlaku pada setiap zaman ternyata selalu merupakan ideologi dari kelas sedang yang berkuasa”. Namun Marx hanya berhenti sampai di sini, karena ia tidak menindaklanjutinya dengan permenungan teologis yang menelurkan kesangsian eksegetis, dengan mempertanyakan agama dan berusaha merubah agama itu. Alih-alih demikian, Marx dengan slogannya yang terkenal “agama adalah candu masyarakat”, justru lebih memilih melenyapkan agama.
Sebaliknya, menurut Teologi Pembebasan, lewat permenungan teologis kita bisa melangkah ke fase berikutnya, “kesangsian ideologis” dan “cara yang kaya dan mendalam dalam menginterpretasikan.” Inilah yang dilakukan oleh Cone, seorang teolog pembebasan dalam konteks masyarakat hitam (sehingga tulisannya pun diberi judul The Black Theology of Liberation). Pertama-tama ia merumuskan realitas sebagai perjuangan pembebasan kelas kulit hitam. Kedua, kesangsian ideologis Cone terhadap pendapat kulit putih bahwa warna kulit jangan dijadikan titik perbedaan demi kesatuan dan universalitas manusia. Ketiga, kesangsian eksegetis Cone terhadap cara berteologi kelas kulit putih yang berpusat pada Kristus yang universal, menutup kemungkinan mendekati Kristus yang juga Yesus yang terikat dengan kebudayaan tertentu. Dan keempat, cara yang kaya dan mendalam mengalami Kitab Suci sebagai Sabda yang relevan bagi perjuangan kelas kulit hitam untuk pembebasan zaman ini.
Terakhir, hal menarik yang bisa dilihat dari Teologi Pembebasan ini adalah muatannya, atau isinya. Menurut F.X. Wahono, setidaknya ada enam pokok bahasan yang dikembangkan di dalam Teologi Pembebasan, yaitu:
1. Kedosaan manusia dalam perspektif perjuangan kelas
2. Kerajaan Allah sebagau utopia yang topia
3. Yesus Kristus sebagai pembebas
4. Gereja rakyat miskin
5. Eksegese dan ekaristi sebagai pusat gereja rakyat
6. Spiritualitas kemiskinan sukarela sebagai jiwa langkah pastoral untuk pembebasan sosial, ekonomi dan politik; pembebasan kemanusiaan; serta pembebasan keputeraan Allah.
Dari enam pokok bahasan yang akan cukup panjang jika diuraikan itu, ada beberapa point penting yang bisa kita petik untuk kepentingan kita, belajar dari Teologi Pembebasan.
Pertama, seperti keyakinan Gustavo Gutierrez, kedosaan manusia tidak hanya berakar dalam hati manusia, melainkan berakar pada struktur sosial, ekonomi, politik, budaya, dan keagamaan yang memeras dan menindas banyak orang miskin demi keuntungan sekelompok kecil masyarakat. Karena itu yang perlu dikedepankan adalah praksis pembebasan pada level sosial, atau dalam bahasa lain, transformasi struktural.
Kedua, upaya pembebasan untuk keluar dari cengkeraman dosa struktural melalui transformasi pribadi dan kolektif harus menghantarkan manusia pada Kerajaan Allah yang menawarkan:
• Pembebasan dari belengu kekerasan ekonomi, sosial dan politik.
• Pembebasan yang menciptakan solidaritas antar manusia.
• Pembebasan dari dosa yang mempersatukan kembali hubungan manusia-Tuhan yang rusak.
Ketiga, gereja yang ideal adalah:
• Gereja yang tidak memandang dirinya sebagai satu-satunya tempat keselamatan
• Gereja harus mengarahkan dirinya untuk pelayanan baru dan radikal bagi seluruh umat manusia.
• Gereja menyadari bahwa karya Kristus dan Roh-Nya adalah kriteria tertinggi bagi kebenaran rencana keselamatan.
Kempat, perlunya gagasan baru tentang pembacaan Injil yang membumi sekaligus menyejarah.
Kelima, perlu adanya pemahaman baru mengenai makna kemiskinan. Lebih teknis, perlu dibedakan antara kemiskinan yang diutamakan yaitu kemiskinan sukarela, dan kemiskinan yang memerlukan praksis pembebasan, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh ketidakadilan struktural dan penindasan.
Menelusuri Akar Pembebasan dalam Islam
Merujuk kepada Nashr Abu Zayd, peradaban Islam adalah sebuah peradaban teks. Dalam pengertian, dasar-dasar ilmu dan kebudayaan Islam tumbuh dan berdiri tegak di atas landasan “teks” sebagai pusatnya. Pada titik ekstrimnya, kecenderungan, atau lebih tepatnya, keunikan peradaban Islam ini, membawa sebagian umat Islam pada cara beragama yang sangat berpaku kepada “teks” semata, dengan mengabaikan realitas sejarah. Agama didekati secara sangat normatif, dari sisi idealitas yang banyak diungkapkan oleh teks itu, sekaligus dengan mengasumsikan “teks”-lah yang harus mengarahkan dan membentuk jalan sejarah.
Padahal – sebagaimana dikatakan Nasr Abu Zayd – teks apapun tidaklah dapat memancangkan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Justru ilmu pengetahuan, kebudayaan maupun peradaban itu sendiri, adalah hasil dialektika manusia dengan realitas, dengan segenap struktur yang membentuknya: ekonomi, sosial, budaya, politik dan sebagainya. Dan pada akhirnya, mempengaruhi teks dan membentuk coraknya.
Menelusuri akar pembebasan dalam Islam, jika kita hanya menggunakan pendekatan teks, sekalipun kita akan mendapatkan hasil yang positif karena didalam teks Islam seperti Al Qur’an dan Sunnah banyak sekali norma dan nilai yang mendukung pembebasan, jelaslah tidak akan memadai. Persoalannya, kita tak akan mendapatkan gambaran yang nyata bagaimana etos pembebasan itu pernah hidup dalam sejarah, bahkan menjadi inti sejarah kelahiran Islam. Bahkan sebaliknya, pendekatan teks semata hanya akan membawa kita pada sebuah kesimpulan seperti yang banyak diyakini oleh kalangan Muslim tekstualis: Tak ada masalah dengan “Islam”. Atau meminjam istilah Teologi Pembebasan, kita tak akan pernah sampai pada “kesangsian ideologis” maupun “kesangsian eksegetis”.
Karena itulah, kita membutuhkan sebuah pendekatan sejarah. Dan analisis yang dikemukakan Asghar Ali Engineer, dalam pandangan penulis, sedikit banyak akan bisa memenuhi kebutuhan kita. Asghar Ali Engineer, seorang Da’i (Penganti Imam yang Ghaib dalam tradisi Syi’ah Ismaililyah) dalam kelompok Daudi Bohras di India, memang terkenal dengan ulasannya mengenai teologi pembebasan dalam perspektif Islam, yang banyak didasarkan pada analisis sejarah.
Mekkah, demikian penuturan Aasghar Ali Engineer, semenjak abad kelima telah menjadi pusat perdagangan internasional yang penting. Kota ini menjadi makmur, karena lokasinya berada pada rute strategis dan menguntungkan dari Arabia Utara ke Arabia Selatan; Mekkah menjadi jalur utama perdagangan dan menjadi pusat pertemuan para pedagang dari kawasan Laut Tengah, Teluk Parsi, Laut Merah melalui Jeddah, bahkan dari Afrika. Dengan demikian Mekkah berkembang menjadi pusat keuangan dari kepentingan internasional yang besar.
Dalam konfigurasi sosial seperti ini, seperti halnya fenomena pertumbuhan negara modern yang menerapkan ideologi pembangunan dan industrialisasi, berkembanglah institusi-institusi pemilikan pribadi, akumulasi keuntungan dan pada akhirnya disparitas ekonomi dan pemusatan kekayaan pada sekelompok orang. Karena cepatnya pertumbuhan operasi perdagangan di Mekkah, beberapa pedagang yang memiliki keahlian yang berasal dari berbagai klan dan suku, terus menerus memperbanyak kekayaan pribadinya. Bahkan mereka membentuk korporasi bisnis antar-suku dan menerapkan monopoli pada kawasan bisnis tertentu di tempat asal mereka.
Menyikapi realitas itu, orang-orang lemah dan tersingkir dari persaingan bebas ini mencoba membentuk asosiasi yang mereka sebut Hilf al-Fudul (Liga Orang-orang Tulus). Dan Nabi Muhammad, pada saat belum menjadi Nabi, ikut aktif dalam lembaga ini.
Demikianlah, perkembangan selanjutnya, kalangan miskin kemudian terpinggirkan dan terlantar dalam belitan dinamika sosial yang tak bisa mereka ikuti. Budaya kesukuan yang semula berkembang di Mekkah pun bergeser menjadi budaya perdagangan, dengan unsur monopolis dan oligarkis di dalamnya. Maka, struktur sosial yang timpang dan rapuh pun menjadi tak terelakkan kemunculannya.
Islam muncul dalam konteks sosial seperti ini. Ia tidak hadir di ruang vakum sejarah. Sebagaimana dinyatakan di dalam Al-Qur'an, Tuhan berjanji untuk mengutus seorang pembimbing atau seorang pemberi peringatan ketika suatu masyarakat menghadapi krisis sosial dan krisis moral. Dan dalam bahasa Ali Engineer, Muhammad dipilih sebagai instrumen kemahabijaksanaan Tuhan untuk membimbing dan membebaskan rakyat Arabia dari krisis moral dan sosial yang lahir dari penumpukkan kekayaan yang berlebih-lebihan sehingga menyebabkan kebangkrutan sosial.
Demikianlah – kembali merujuk Ali Engineer - Islam bangkit dalam setting sosial Mekkah, sebagai sebuah gerakan keagamaan, namun lebih dari itu, ia sesungguhnya sebuah gerakan transformasi dengan implikasi sosial ekonomi yang sangat mendalam. Islam, dengan kata lain, menjadi tantangan serius bagi kaum monopolis Mekkah.
Menarik untuk dicatat, karena kemudian sejarah menegaskan bahwa orang-orang yang menentang Nabi – direpresentasikan oleh Abu Lahab, Abu Jahal dan Abu Sofyan - kebanyakan berasal dari kelas mapan di Mekkah, dan penentangan itu lebih didasarkan pada sifat transformatif Islam yang akan merugikan kepentingan ekonomi mereka, dibandingkan ketidaksetujuan mereka terhadap ajaran penyembahan kepada Tuhan. Sebagaimana kita tahu, Islam dengan tegas menentang akumulasi keuangan yang selama ini banyak dilakukan kalangan mapan Mekkah.
Al Qur’an misalnya menyebutkan:
"Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia mengira bahwa harta itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak! Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam Huthomah. Dan tahukan kamu Huthomah itu? (yaitu) api (yang disediakan) Allah yang dinyalakan, yang (membakar) sampai ke ulu hati." (Surat 104)
Demikianlah, Nabi Muhammad semenjak fase kenabiannya memang banyak mengedepankan idiom-idiom teologis, tapi orientasinya adalah perubahan struktural di Mekkah. Kepeduliannya adalah bagaimana perbudakan, penindasan kalangan kaya terhadap kaum miskin, juga pelecehan terhadap kaum wanita dan struktur sosial yang tidak adil lainnya bisa diatasi. Karena itu pulalah, kita bisa melihat fakta sejarah bahwa gerakan Nabi lebih banyak didukung oleh mereka yang tertindas, kalangan budak dan orang-orang miskin, seperti Bilal, Yassar dan istrinya Sumayyah, Salman al Farisi, Miqdad al Amr, Abu Dzar al Ghifari dan lainnya. Sebab kalangan ini melihat harapan dan masa depan mereka ada pada gerakan pembebasan yang dipimpin Nabi Muhammad. Sekalipun pada akhirnya, kita tidak bisa mengingkari peranan orang-orang yang dalam kategori sosiologis modern adalah dari kalangan kelas menengah seperti Ali bin Abu Tholib, Abu Bakar maupun Umar dan Utsman. Bahkan agaknya kita bisa menyebutkan mereka sebagai “intelektual organis” dalam istilah Marian Hillar.
Teologi Islam yang Membebaskan: Tuntutan Masa Kini
Persoalan yang melanda dunia Islam adalah, etos pembebasan ini tidak bertahan lama. Ketika Nabi wafat, demikian pula sahabat-sahabat utama - yang sekalipun pernah terlibat dalam konflik politis secara umum tetap menjaga nilai-nilai substantif Islam - wafat satu persatu, dan otoritas politik atas masyarakat Islam jatuh ke tangan Dinasti Umayyah yang menjalankan kekuasaan yang otokratis dan feodalistik, bergeserlah bandul sejarah. Elan pembebasan mengalami kerusakan berat, dan yang kemudian berkembang adalah kekuatan eksploitatif dan tiranik yang terlembaga. Dan dalam atmosfer sosial politik seperti inilah kemudian tumbuh bangunan keilmuan Islam, termasuk di dalamnya ilmu kalam yang bisa disetarakan dengan teologi.
Beranjak dari penghayatan realitas sejarah masyarakat Islam saat ini yang banyak diwarnai oleh penindasan secara fisik maupun non-fisik (seperti kepada kalangan wanita, non-muslim dan masyarakat awam), ketimpangan pemilikan sumber-sumber daya ekonomi dan politik, juga hegemoni militer dan militerisme, layaklah kita mengedepankan kritisime, yang analog dengan kesangsian ideologis dan kesangsian eksegetis dalam Teologi Pembebasan. Kita patut mempertanyakan superstruktur – khususnya “tafsir agama” - yang kini banyak berkembang, karena sebagaimana ditunjukkan beberapa kajian sosiologi agama , seperti oleh Max Weber, Robert N. Bellah maupun Clifford Geertz, ada benang merah yang menghubungkan corak tafsir agama dengan realitas dan struktur sosial.
Tepat pada titik inilah menjadi relevan bagi kita, untuk mengembangkan proyek perumusan model beragama – tepatnya metode teologi – yang mengarah pada pembebasan. Baik pembebasan dari struktur sosial yang hegemonik dan menindas, pembebasan dari “kegelapan kemanusiaan pada tataran individual maupun sosial”, maupun pembebasan dari belengu tafsir agama yang tercipta dalam konteks tertentu di masa lalu.
Pendalaman akan topik ini, yang akan membawa kita pada gagasan-gagasan revolusioner seperti yang diajukan Mohammed Arkoun dengan kritik nalar Islam dan Mohammed Abid al-Jabiri dengan kritik nalar Arabnya, akan dilakukan dalam tulisan yang lain. Yang ingin dicapai dalam tulisan ini hanyalah sebuah kesadaran, bahwa kita membutuhkan sebuah model beragama yang memicu kita pada praksis pembebasan, karena dari berbagai sisi, termasuk karena kesamaan sebagai bagian dari Dunia Ketiga, konteks sosial masyarakat Islam secara umum, ataupun masyarakat Indonesia, memiliki banyak kemiripan dengan konteks sosial masyarakat Amerika Latin dimana tumbuh Teologi Pembebasan.
Rujukan:
Asgar Ali Engineer, Islam dan Pembebasan, versi online di Media-Isnet.
F.X. Wahono Nitiprawiro, Teologi Pembebasan: Sejarah, Metode, Praksis dan Isinya, Yogyakarta: LkiS, Cetakan I Tahun 2000
Marian Hillar, Liberation Theology, artikel internet koleksi penulis.
Nasr Abu Zayd, “Tekstualitas Al Qur’an”, Yogyakarta: LkiS, Cetakan II tahun 2002
Ron Rhodes, Liberation Theology, artikel internet koleksi penulis.


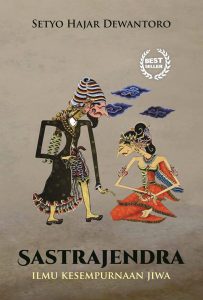
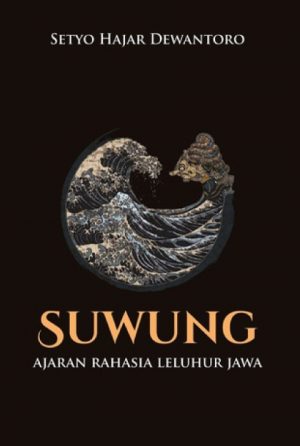

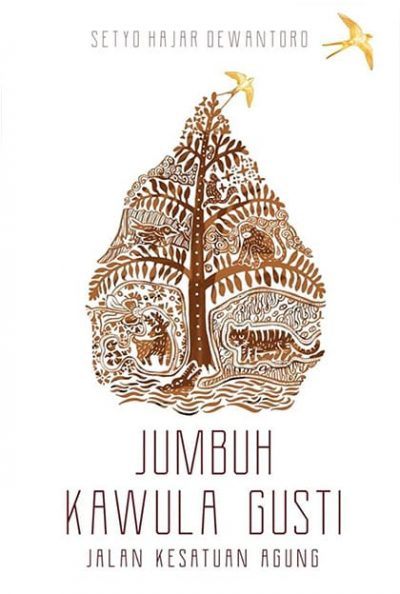
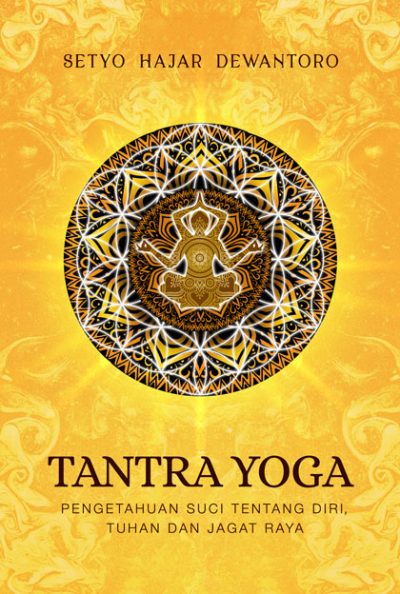
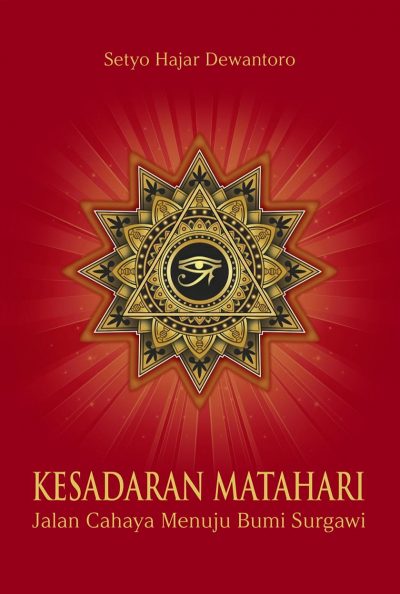









Post a Comment