“Jika kita mengunjungi penjara, tempat-tempat pelacuran, serta rumah sakit-rumah sakit jiwa, kemudian mengunjungi sekolah-sekolah untuk menghitung orang-orang yang gagal, para biang kerok, ekstremis-ekstremis politik, dan orang-orang yang dengan kelakukan abnormal, kita akan dengan pasti melihat bahwa kebanyakan individu semacam itu kehilangan ketenangan keluarga. Mereka tidak memiliki rumah yang tenteram, di mana semestinya ada ayah yang sayang serta ibu yang baik serta tidak berlebihan dalam kemewahan dan kekerasan. Kerusakan rumah yang demikian telah menciptakan potret kekacauan sosial semacam itu serta lahirnya generasi tanpa tujuan dan berantakan.”
(M. al Jarmud, Home and School)
Saya nyaris sepenuhnya setuju dengan pandangan di atas. Nyaris, karena pada faktanya ada individu-individu tertentu yang bisa melepaskan diri dari jeratan keadaan, lingkungan dan masa lalu mereka. Individu-individu tersebut memang punya latar belakang keluarga yang tidak mendidik – bahkan bisa dibilang berantakan, tapi dengan tingkat kemandirian tertentu, mereka bisa hadir di tengah masyarakat sebagai kelompok terdidik sekaligus terhormat dalam makna sebenarnya. Sebaliknya, ada juga individu yang berlatar keluarga harmonis dan terdidik, justru berkembang menjadi anggota masyarakat yang mengidap penyakit sosial.
Tapi, saya sepenuhnya setuju dengan sinyalemen umum yang bisa kita petik dari pandangan di atas, bahwa fenomena bangsa dan masyarakat yang sakit, tidak bisa dilepaskan dari fenomena keluarga yang sakit. Ditarik ke keadaan sosial kita dewasa ini, saya percaya bahwa salah satu akarnya adalah karena memang kebanyakan keluarga di tengah masyarakat kita, tidak lagi berfungsi sebagai institusi pendidikan yang baik.
Fenomena Keluarga Modern
Apa yang bisa diberikan kepada anak-anak oleh sepasang suami istri yang waktu dan energinya tersedot habis untuk mencari nafkah? Di kota-kota besar (maupun kecil) yang tuntutan kehidupannya membuat banyak orang menjerit, bukanlah hal yang aneh, pasangan suami istri mesti keluar rumah ketika matahari baru menyingsing, dan kembali ke rumah ketika matahari telah terbenam. Hal demikian menjadi rutinitas keseharian. Dan anak-anak yang dilahirkan pasangan tersebut, biasanya tumbuh berkembang dalam asuhan pihak lain. Entah itu sekolah, televisi, lingkungan pergaulan, maupun yang lainnya.
Apakah ini merupakan fenomena yang positif? Jawabannya bisa disimpulkan dari kenyataan keseharian yang bisa kita saksikan bersama. Banyaknya remaja yang terjebak dalam kenakalan bahkan kriminalitas, gadis-gadis muda (maupun para pemuda) yang terjebak dalam pergaulan bebas, menunjukkan merebaknya krisis nilai di kalangan generasi muda. Mengapa ini terjadi? Sebab ada kegagalan dalam proses penyampaian nilai-nilai dan kearifan hidup dari generasi sebelumnya. Ada komunikasi yang terputus. Orang tua yang serba sibuk mengandaikan proses penyampaian nilai – yang berorientasi pada pembentukan karakter anak – bisa dilakukan oleh sekolah. Pada faktanya, kebanyakan sekolah lebih berfungsi sebagai institusi pengajaran. Anak memang berkembang dimensi kognitifnya. Tetapi pada dimensi lain, yaitu afektif, yang menyangkut watak, karakter, sikap, kebanyakan generasi muda kita laksana anak-anak yatim yang kehilangan pengasuh. Mereka tak bisa menghayati nilai-nilai kebajikan dan kearifan hidup yang sesungguhnya diajarkan di sekolah, sebab minimnya teladan.
Sementara kebanyakan orang tua modern, barangkali lebih menjadikan rumah sebagai tempat melepas letih setelah energi mereka tersedot oleh pekerjaan kantor maupun bisnis. Agenda mendidik anak, kiranya membutuhkan energi, konsentrasi, waktu dan kesiapan fisik mental yang tidak sedikit. Tentu saja, agenda ini pada akhirnya tak lagi sempat dilaksanakan oleh kebanyakan keluarga modern yang kehabisan energi ketika kembali ke rumah.
Kebanyakan anak-anak kita, pada dasarnya tumbuh berkembang dalam kesendirian. Teramat wajar jika kemudian, mereka menjadi dewasa dengan kepribadian yang seringkali asing di mata orang tua mereka.
Sebetulnya, yang menjadi masalah bagi keluarga modern bukan sekadar ketiadaan waktu yang memadai untuk mendidik anak-anak mereka. Melainkan juga soal visi dan cara pandang. Di tengah masyarakat yang tengah terpesona dengan dinamika kebudayaan materialistis, semakin jaranglah keluarga yang punya cukup perhatian pada hal-hal yang filosofis dan membutuhkan perenungan mendalam. Cara pandang bahwa cukuplah sudah kita berbicara tentang kenikmatan lahiriah dari titik kelamin hingga perut, agaknya demikian mencengkeram. Banyak orang tua yang akibat pendidikan dan pengaruh kebudayaan modern, kehilangan kontak dengan kebudayaan dan nilai-nilai masa lalu yang sejatinya luhur. Lebih lugasnya, mereka kehilangan jati diri. Mereka terlepas dari identitas kultural mereka yang asli.
Apa yang bisa diajarkan oleh orang tua semacam ini? Jelas tak lebih dari sekadar kekosongan. Mereka hanya bisa menyampaikan pesan-pesan tanpa makna, kata-kata yang tak bisa memasuki jiwa.
Peran Orang Tua
Yang pertama kali harus ditegaskan adalah bahwa para orang tua tak bisa terlepas dari kewajiban mendidik anak-anak mereka. Para orang tua harus bekerja keras untuk menjadikan keluarga sebagai sekolah yang pertama dan utama bagi anak-anak mereka.
Baqir Muhammad al Qarashi, dalam bukunya Seni Mendidik Islami mencatat tiga kewajiban utama para orang tua: Pertama, menyelamatkan faktor-faktor ketenangan, cinta kasih serta kedamaian dalam rumah, dan menghilangkan segala macam kekerasan, kebencian, serta antagonisme. Kedua, mengawasi proses-proses pendidikan. Keluarga harus bertanggung jawab dalam berbagai proses pendidikan sosial, yang melalui mereka, anak-anak mendapatkan ahli serta pengatur budaya yang memungkinkan mereka menerima lebih dan lebih, serta membuat mereka cukup pas untuk berhubungan dengan masyarakat. Ketiga, menanamkan emosi yang benar, kesucian, kebaikan-kebaikan dan kecenderungan moral yang berguna bagi pencapaian masa depan yang baik.
Apakah yang sesungguhnya diharapkan oleh orang tua dari anak-anaknya? Kiranya semua akan menjawab, “Kehidupan yang baik.” Masalahnya adalah, apakah prasyarat tercapainya kehidupan yang baik oleh anak-anak kita? Seorang anak membutuhkan berbagai hal agar bisa mencapai kehidupan yang baik. Mulai dari watak dan karakter yang baik sehingga dia bisa hidup dan berhubungan secara wajar dengan masyarakat, hingga ilmu untuk menyiasati beragam tantangan kehidupan. Orang tualah yang punya tanggung jawab untuk menyediakan sekolah bagi anak-anak agar mereka memperoleh apa yang mereka butuhkan. Tapi, alangkah malangnya anak-anak ketika para orang tua mereka mengelak dari tanggung jawab, dengan melimpahkan pekerjaan mendidik kepada pihak lain. Yang sering terjadi misalnya, orang tua merasa sudah berbuat yang terbaik ketika bersedia membayar mahal untuk menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah unggulan yang mahal. Sementara mereka sendiri sibuk dengan dunia mereka, berupa karier pekerjaan, bisnis maupun dunia kesenangan, yang membuat mereka tak punya cukup waktu untuk bersama anak-anak mereka. Sungguh, tindakan seperti ini bukan tindakan yang bisa dibenarkan. Sekolah unggulan semahal apapun, tak bisa memberikan kasih sayang, kehangatan dan keteladanan yang akan membangun mentalitas anak sebagaimana yang bisa diberikan oleh seorang ayah dan ibu.
Kitalah para orang tua, yang harus menjadi guru pertama dan utama bagi anak-anak kita. Bukan orang lain. Imam Zainal Abidin berkata, “Hak anakmu ialah bahwa engkau menyadari keberadaan mereka menjadi bagian dari dirimu dan melekat padamu dalam kebaikan dan keburukan. Engkau bertanggung jawab memberikan sifat-sifat mulia, mengenalkan mereka pada Allah, serta mendorong mereka agar dengan rela menyembah-Nya bersamamu. Segalanya diganjar atau dihukum. Engkau harus berbuat baik pada anak-anakmu sebagaimana para pencari imbalan baik di dunia ini, serta menyesuaikan mereka dengan kehendak Allah melalui pengawasan dan latihan.”
Sementara itu Imam Al Ghozali mengatakan, “Memilih metode pendidikan tertentu merupakan salah satu tugas penting serta berharga. Seorang anak adalah amanah ayahnya. Hatinya yang tidak bernoda merupakan mutiara berharga yang bersih dari segala bentuk atau gambar. Ia menjadi cocok untuk menerima segala bentuk serta mengikuti jalan apapun. Jika seorang anak terbiasa pada kebaikan, hal ini akan terpatri di dalam benaknya, dan kebaikan dunia ini maupun hari kemudian akan terhimpun untuknya. Orang tua, para guru dan pembina anak memiliki bagian dalam ganjaran ini. Sebaliknya jika seorang anak terbiasa pada keburukan, dan terabaikan sebagaimana hewan, kegagalan serta kerugian akan menjadi hasilnya. Walinya akan berdosa karena salah membimbing. Allah SWT berfirman, “ Wahai orang-orang beriman, jagalah keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batu; yang di atasnya adalah malaikat-malaikat yang keras serta kuat, mereka tidak mengingkari Allah dengan apa yang Dia perintahkan pada mereka, serta melakukan sebagaimana yang telah diperintahkan.”
Tentu saja, di luar pembentukan karakter, ada tugas tambahan yang tak kalah penting. Orang tua juga berkewajiban memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak yang bersifat lahiriah. Anak-anak membutuhkan uang, tempat tinggal, makanan yang bergizi, dan pakaian yang layak. Kerja keras dari orang tua agar kebutuhan ini terpenuhi, menjadi bagian dari pemenuhan amanat kepada Allah SWT yang telah bermurah hati memberikan buah hati kepada kita.
Kelanggengan Cinta Sebagai Fondasi
Menyediakan rumah yang memberikan kenyamanan secara fisik dan psikologis bagi anak-anak, sekaligus mampu berfungsi sebagai sekolah di mana anak-anak mempelajari ilmu-ilmu mendasar untuk kehidupan di masa datang, adalah tugas bersama suami dan istri. Suami dan istri perlu mengupayakan diri mereka masing-masing agar menjadi ayah dan ibu yang dibanggakan anak-anak mereka karena mampu memberikan keteladanan. Mereka berdua punya kewajiban memupuk cinta dan kasih sayang secara terus menerus, dan merefleksikannya ketika berhubungan dengan anak-anak mereka.
Keluarga akan menjadi neraka bagi anak-anak, ketika suami dan istri tak bisa bekerjasama lagi dengan baik. Terlebih ketika di antara mereka mulai terbiasa bertengkar, saling tidak percaya, dan hidup dalam hubungan yang serba hambar. Anak-anak bisa merasakan pahitnya memiliki ibu dan ayah yang tak lagi saling mencintai dan tak lagi menjadi partner yang saling mendukung.
Langgengnya cinta dan kasih sayang antara suami dan istri merupakan fondasi bagi terbentuknya keluarga sebagai institusi pendidikan bagi anak-anak. Baik suami maupun istri membutuhkan cinta dan kasih sayang dari pasangan masing-masing agar hidup mereka berenergi dan kondisi psikologis mereka stabil. Tanpa stabilitas emosional dan keberlimpahan energi yang terefleksikan dalam hidup yang penuh spirit, orang tua tak akan bisa menjadi guru yang baik bagi anak-anak.
Di sinilah pentingnya menguasai seni melanggengkan cinta dan kasih sayang bagi suami dan istri. Bagaimana Anda bisa senantiasa mencintai istri atau suami Anda? Cinta dan kasih sayang yang tulus kepada pasangan merupakan prasyarat untuk mendapatkan balasan cinta dan kasih sayang yang setimpal. Suami atau istri harus mencintai dan mengasihi pasangan masing-masing tanpa mengharapkan balasan, justru agar balasan itu hadir. Ketika kita mencintai dan mengasihi dengan pamrih, biasanya segala sesuatunya akan menjadi kacau.
Banyak kasus ketidakharmonisan suami istri berawal dari sikap masing-masing yang serba menuntut. Kita terbiasa meminta, bukan memberi. Ketika masing-masing mendahulukan sikap meminta, lalu siapa yang akan mulai memberi? Ketika suami atau istri tak memperoleh apa yang mereka harapkan dari pasangan mereka, tumbuhlah benih-benih kefrustasian. Komunikasi menjadi tersendat. Hubungan menjadi tak lagi seindah ketika pertama kali merenda rumah tangga. Ujungnya orang tua akan tersedot dalam suasana konflik, energi maupun waktu mereka akan habis, lalu tak sanggup lagi untuk menjadi pendidik yang baik bagi anak-anak mereka.
Menarik untuk mengutip ungkapan Dalai Lama, “ Sekarang, ketika orang berbicara tentang sifat pengasih, menurut saya sering ada bahaya mencampuradukkan sifat pengasih dengan keterikatan. Maka bila kita berbicara tentang sifat pengasih, kita mula-mula harus membedakan antara dua macam cinta atau rasa kasihan. Ada sikap kasih yang diwarnai dengan keterikatan atau pamrih – keinginan untuk mengendalikan seseorang, atau menyayangi seseorang agar orang itu balas menyayangi Anda. Sikap kasih yang lazim dijumpai seperti ini tidak utuh dan melenceng dari makna yang sejati. Dan hubungan yang didasarkan pada kasih seperti itu saja tidak akan stabil. Hubungan yang tidak utuh macam ini, yang didasarkan pada penerimaan dan pengenalan seseorang sebagai teman (atau orang dekat, atau kekasih) bisa menjurus pada suatu keterikatan emosional dan rasa akrab. Akan tetapi begitu ada perubahan situasi sedikit saja, silang pendapat misalnya, atau bila sang teman (atau sang orang dekat dan kekasih) melakukan sesuatu yang membuat Anda marah, proyeksi mental Anda akan berubah secara tiba-tiba; artinya, ia tidak lagi menjadi teman (atau orang dekat, atau kekasih) saya.
Dalai Lama melanjutkan, “Akan tetapi ada kasih jenis kedua yang bebas dari keterikatan semacam itu. Itulah kasih sejati. Kasih semacam ini tidak terlalu banyak didasarkan pada kenyataan bahwa orang ini atau orang itu baik kepada saya. Sebaliknya, kasih yang sejati didasarkan pada pola pikir bahwa semua orang punya hasrat bawaan untuk bahagia dan mengatasi penderitaan seperti saya sendiri. Dan seperti saya sendiri, mereka memiliki hak yang wajar untuk memenuhi aspirasi mendasar tadi. Berdasarkan pengenalan terhadap kesamaan dan keserupaan ini, Anda mengembangkan suatu rasa dekat dan akrab dengan orang lain. Dengan menjadikannya sebagai fondasi, Anda akan merasakan kasih, tidak peduli apakah Anda memandang orang lain itu sebagai teman ataukah sebagai musuh.
Akhinya, kita meloncat pada kesimpulan Dalai Lama, “Maka, orang dapat melihat bagaimana perbedaan antara dua macam kasih ini dan upaya menumbuhkan kasih sejati bisa penting sekali dalam kehidupan sehari-hari kita. Sebagai contoh, dalam perkawinan umumnya ada unsur keterikatan emosional. Akan tetapi, menurut saya, jika unsur kasih sayang yang sejati juga ada, yang didasarkan sikap saling hormat sebagai sesama manusia, perkawinan itu berpeluang untuk langgeng. Apabila keterikatan emosional di dalamnya tidak disertai kasih yang sejati, perkawinan tidak mantap dan cenderung cepat berakhir.”
Jika kita meyakini bahwa rumah kita mesti menjadi istana kasih sayang bagi anak-anak agar mereka tumbuh berkembang dengan jiwa yang mantap, kita semua kiranya perlu belajar bagaimana bisa mencintai dan mengasihi secara benar. Mula-mula kepada pasangan, dan ketika anak-anak lahir, kita meluaskan cinta dan kasih sejati tersebut kepada mereka.
Semoga kita bisa melahirkan generasi baru yang mampu hidup berbahagia.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)


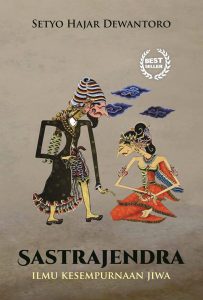
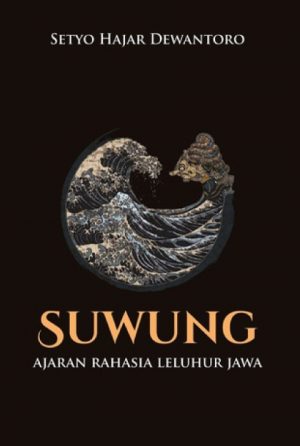

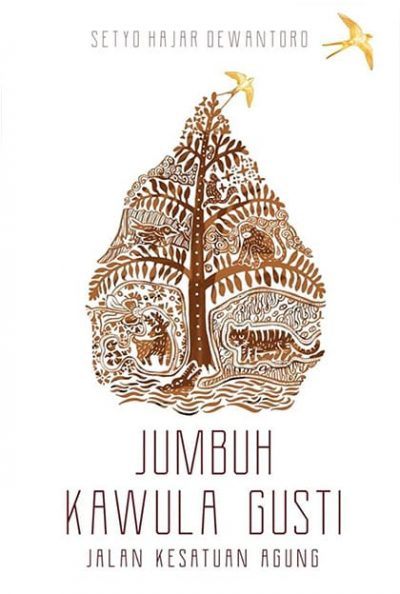
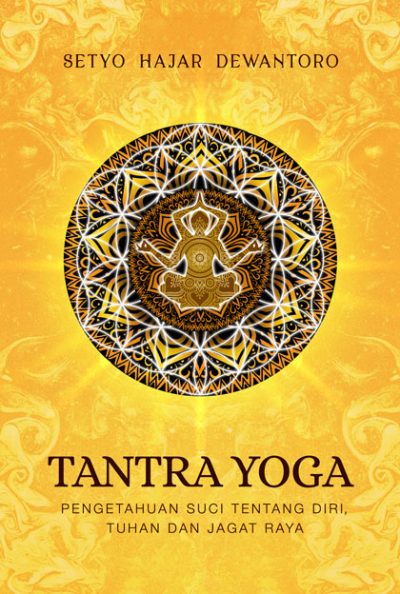
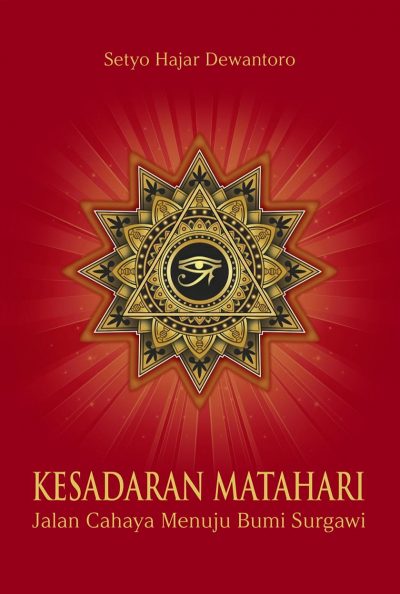









mendidk anak sangat berpengaruh dalam hal keluarga dalam masa perkembanga tahap-tahap awal anak-anak sampai pertengahan dan akhir anak.salam kenal, berkunjung balik ya
ReplyDelete