
Pendidikan, diyakini banyak pihak sebagai instrumen penting untuk mewujudkan tatanan masyarakat sejahtera. Bagaimana sejatinya gambaran pembangunan pendidikan yang diselenggarakan di Indonesia? Tulisan di bawah ini coba membahas berbagai problematika yang terjadi di tingkat praktis dan beberapa solusi untuk mengatasinya.
Pendidikan sebagai Instrumen Penyiapan SDM
Secara garis besar, pendidikan sebagai pelembagaan upaya-upaya pengembangan sumber daya manusia punya korelasi yang kuat dengan perkembangan ekonomi dan pencapaian kesejahteraan masyarakat. Professor Harbison – sebagaimana dikutip Michael P. Todaro dalam buku ilmu ekonominya – menjelaskan bahwa, “Sumber daya manusia ....merupakan landasan utama negara-negara kaya. Sumber daya modal dan alam merupakan faktor-faktor produksi yang pasif, sedang manusia merupakan faktor aktif yang dapat mengakumulasi modal, mengolah sumber daya alam, membangun organisasi sosial, ekonomi dan politik serta melaksanakan pembangunan nasional lebih lanjut. Jelasnya, suatu negara yang tidak mampu mengembangkan dan pengetahuan serta kecakapan penduduknya maupun memanfaatkannya secara efektif di dalam ekonomi nasional berarti tidak akan mampu mengembangkan apapun juga.”
Namun, pencarian model pendidikan seperti apa yang punya korelasi positif dengan peningkatan perekonomian, penanggulangan kemiskinan dan pencapaian kesejahteraan masyarakat di dunia ketiga, justru menghadirkan banyak pertanyaan. Sejauh ini, upaya perluasan pendidikan yang dilakukan di negara-negara dunia ketiga, memang membawa hasil. Tapi itu dalam bentuk output yang berkaitan langsung dengan pendidikan: meningkatnya jumlah penduduk yang bersekolah dan melek huruf. Sementara soal dampak ekonomis dari pendidikan itu, kita menemukan problema yang belum terselesaikan. Seperti dinyatakan oleh Michael P. Todaro, “Setelah hampir 3 dekade berkecimpung dalam usaha perluasan pendidikan dan ratusan milar dollar telah dikeluarkan untuk biaya pendidikan, keadaan yang menyedihkan pada rata-rata penduduk Asia, Afrika dan Amerika Latin tampak hanya sedikit membaik. Kemiskinan absolut demikian kronisnya. Disparitas ekonomi antara kaya dan miskin semakin melebar setiap tahunnya. Pengangguran dan setengah pengangguran telah mencapai proporsi yang mencemaskan, yaitu dengan meningkatnya orang-orang terdidik tanpa pekerjaan.”
Pada konteks Indonesia secara umum, kita melihat fenomena yang menarik. Seiring dengan laju modernisasi, pendidikan terutama yang formal, mengalami perkembangan demikian pesat. Upaya masyarakat menyesuaikan diri dengan tuntutan modernisasi – yang salah satunya berupa standarisasi keahlian untuk memasuki dunia kerja yang disimbolkan oleh selembar ijasah atau sertifikat – membuat demand terhadap pendidikan meningkat. Dan ini diimbangi oleh supply jasa pendidikan: sekolah mulai dari TK hingga perguruan tinggi, baik yang dikelola swasta maupun negara bermunculan dan berkembang pesat. Mereka yang melek huruf memang meningkat, jumlah anak sekolahan atau kalangan terdidikpun bertambah. Tapi itu tak mengubah drastis angka kemiskinan dan pengangguran. Perbedaannya cuma satu: dulu kalangan miskin dan pengangguran kita adalah kaum tak bersekolah, kini mereka menyandang staus anak sekolahan, baik yang sempat bersekolah hingga tingkat SD saja maupun yang berhasil lulus perguruan tinggi. Dengan kata lain, meluasnya pendidikan secara umum “berhasil” menambah jumlah orang miskin dan pengangguran yang terdidik.
Mengapa ini terjadi? Lapangan kerja yang tersedia, tak sebanding dengan ketersediaan tenaga kerja yang dipasok berbagai institusi pendidikan. Anak sekolahan yang tak tertampung di dunia kerja inilah yang kemudian menjadi “orang miskin” dan “pengangguran baru”.
Memang kita tak memungkiri fakta bahwa pendidikan – dalam hal ini adalah pendidikan formal – telah menjadi tangga mobilisasi vertikal: tempat orang mengubah nasib. Namun tampaknya ini hanya berlaku untuk segelintir orang. Fenomena yang lebih sering terjadi, pendidikan justru menjadi potren di mana kita bisa menemukan kemiskinan yang melingkar-lingkar. Seiring dengan makin tingginya demand terhadap pendidikan dan kiat pelitnya negara memberi subsidi pendidikan, biaya yang ditanggung masyarakat untuk mengenyam pendidikanpun menjadi kian tinggi. Baik jika dihitung dalam nilai nominal, maupun jika dihitung proporsinya terhadap pengeluaran secara keseluruhan dari sebuah keluarga. Ini menyebabkan, akses terhadap pendidikan menjadi sangat terbatas.
Hanya orang yang punya uang – dan sedikit orang miskin yang beruntung - yang bisa mengakses pendidikan setinggi-tingginya. Sementara kalangan miskin sebagian besarnya tak bisa meneruskan pendidikan lanjutan hingga perguruan tinggi karena terantuk oleh biaya. Karena pendidikan yang dienyam orang miskin cenderung lebih rendah dibandingkan yang bisa dienyam orang kaya, maka ketika masuk ke dunia kerjapun, mereka kalah bersaing. Mereka pada akhirnya lebih banyak menempati posisi pekerja rendahan sesuai tingkat pendidikan mereka. Sebagian yang beruntung bisa menjadi pekerja rendahan, dan itu artinya menjadi orang miskin juga karena gajinya pun rendah – seringkali bahkan tak mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Sementara yang tak tertampung di sektor pekerjaan formal, sebagian menganggur, sebagian lain mengadu nasib di sektor informal. Sebagian kecil mereka bisa sukses, usahanya berkembang dan nasibnya membaik. Tapi, sebagian besar lainnya – karena ternyata kebijakan pemerintah juga tak terlalu memihak kepada pencari sesuap nasi di sektor informal – nasibnya seringkali memilukan. Mereka jadi “pesakitan” pembangunan dan tetap menjadi orang miskin.
Kalaupun ada orang miskin yang bisa menyamai orang kaya dalam mengakses pendidikan yang tinggi, tetap saja, karena mereka kalah dalam hal jaringan dan tradisi, di dunia nyata - yaitu ketika mereka harus mulai mencari kerja dan bekerja, cenderung untuk kalah juga.
Secara lebih kongkrit, mari kita simak data kasar berikut, hasil observasi di Kota Cirebon. Jumlah lulusan SLTA di Kota Cirebon mencapai 4.000 – 5.000 orang. Dari jumlah itu, yang melanjutkan ke perguruan tinggi sekitar 20 %. Sebanyak 10 % memilih bekerja di berbagai perusahaan, atau memasuki sektor-sektor informal: berdagang voucher HP, berjualan bakso, dan sebagainya. Sementara sisanya yang sekitar 70 % memilih menganggur di rumah. Kemudian, mereka yang melanjutkan ke perguruan tinggi, hanya sekitar 10-20 %-nya yang benar-benar mendapatkan kesempatan belajar di perguruan tinggi bermutu dan ternama sehingga jaminan kerja setelah lulusnya lebih pasti. Sementara sisanya belajar di perguruan tinggi yang kurang ternama sekaligus kurang bermutu. Yang terakhir ini, biasanya hanya sebagian kecil yang terserap di dunia kerja, sebagian besar lainnya setelah lulus tetap sulit mendapatkan pekerjaan, enggan berwirausaha mandiri dan akhirnya jadi sarjana pengangguran.
Realitas sebagaimana tergambar di atas, menantang kita untuk menemukan formula kebijakan dan desain pendidikan yang tepat. Kita perlu merancang pendidikan yang egaliter dalam pengertian mudah diakses siapapun termasuk orang-orang miskin yang berdaya beli rendah. Saat yang sama, pendidikan tersebut juga bisa menjamin, para peserta didik yang telah menghabiskan waktunya untuk belajar, bisa memetik buahnya. Yaitu bahwa pengetahuan dan keterampilan yang mereka kuasai bisa mereka terapkan untuk mencari uang – tanpa kendala keterbatasan lapangan kerja, dan merekapun bisa “terentaskan” dari kemiskinan.
Antara Perluasan Akses dan Peningkatan Mutu Pendidikan
Kiranya semua pihak sepakat, bahwa salah satu tugas bersama kita adalah meningkatkan mutu pendidikan. Karena hanya dengan cara demikianlah, kita bisa melahirkan generasi baru yang bisa berperan sebagai pemberi solusi terhadap rajutan problem sosial di kota ini yang kian rumit.
Sebagian pihak mengkaitkan ide peningkatan mutu pendidikan ini dengan desakan menaikkan alokasi anggaran pendidikan. Yang nyaring terdengar adalah tuntutan agar alokasi anggaran pendidikan di tingkat pusat dan daerah adalah 20 %. Ide lainnya adalah sekolah gratis: beban warga miskin diambil alih oleh negara melalui mekanisme beasiswa maupun subsidi. Sampai tingkatan tertentu, gagasan-gagasan demikian mulai diadopsi di Kota Cirebon. Dinas Pendidikan merupakan SKPD yang paling banyak mengelola dana APBD. Kebijakan pembebasan uang sekolahpun mulai digulirkan, setidaknya di tingkatan SD.
Pertanyaannya, sahihkah gagasan ini? Tampaknya banyak hal yang harus kita pikirkan dahulu secara jernih agar kita tak terjebak pada kesalahan berpikir, lalu melahirkan kebijakan yang salah.
Pertama, menyangkut ide sekolah gratis. Gagasan ini harus benar-benar ditanggapi secara kritis. Mengapa? Mari kita pikirkan. Pengalihan beban biaya sekolah dari warga kepada pemerintah pusat/daerah, pada prakteknya akan melahirkan dilema pada anggaran. Terlebih jika langkah efisiensi biaya di sektor pendidikan tidak dilakukan terlebih dahulu. Pertama, otomatis pengalihan beban melejitkan alokasi anggaran untuk penididikan yang konsekuensinya adalah pengurangan alokasi anggaran untuk sektor lain. Celaka jika yang dikurangi adalah sektor yang punya daya ungkit tinggi seperti sektor pembangunan infrastruktur dan penataan lingkungan, sementara mutu program di sektor pendidikan sendiri sulit dipertanggungjawabkan. Kecuali, jika pihak birokrat dengan lapang hati melakukan efisiensi anggaran yang terkait dengan kepentingan mereka sendiri. Ini sepertinya bukan hal yang masuk akal untuk saat ini. Kedua, jika geser menggeser menjadi tidak mungkin, yang bisa dilakukan adalah meningkatkan pendapatan negara/pemda. Melalui apa? Pajak tentunya. Nah, jika ini yang terjadi, pada hakikatnya tetap rakyat pula yang harus membiayai pendidikan, sekalipun menjadi tidak langsung.
Lebih jelasnya, ketika berbicara soal pembangunan di sektor pendidikan, kita sesungguhnya berhadapan dengan dua tantangan: perluasan akses pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan. Ide sekolah gratis dan semacamnya, merupakan wujud kongkrit dari gagasan perluasan akses pendidikan. Kebijakan perluasan akses pendidikan sesungguhnya sangat positif, jika itu dilaksanakan sejalan dengan peningkatan mutu pendidikan. Jika mutu pendidikan baik, semakin banyak yang mengakses pendidikan, akan semakin baik hasilnya. Tapi, jika mutu pendidikan buruk, lebih baik sebetulnya jika semakin banyak yang tidak bisa mengakses pendidikan tersebut. Mengapa? Sebab pendidikan yang tidak bermutu, alih-alih memberdayakan dan membuat anak didik menjadi mandiri, justru malah mematikan karakter dan memandulkan segenap daya kemanusiaan yang dimiliki anak didik.
Sejauh observasi oleh penulis, bisa disimpulkan bahwa pendidikan yang dijalankan di mayoritas sekolah di daerah yang diobservasi, yaitu Kota Cirebon, masih jauh dari standar ideal. Di kebanyakan sekolah, anak-anak didik cenderung sekadar disuruh menghafal pelajaran sebagai persiapan ulangan dan ujian, bukannya dibimbing untuk memahami dan menghayati pelajaran secara kontekstual sehingga pelajaran itu bisa diterapkan di masa depan demi pencapaian kesejahteraan pribadi, keluarga dan masyarakat. Pelajaran biologi misalnya, sekadar diisi dengan kegiatan menghafal nama-nama organ manusia, tumbuhan dan hewan. Nyaris tanpa bimbingan kontekstual tentang bagaimana pelajaran seputar organ manusia membantu anak untuk bisa mengenal tubuh sendiri lantas terdorong untuk merawat dan menjaga kesehatan tubuh. Atau tentang bagaimana pelajaran seputar organ tumbuhan dan hewan membantu si anak untuk bisa bertani dan beternak setidaknya di lahan pekarangan. Pendidikan berbasiskan kegiatan menghafal dan tidak kontekstual, jelas akan melahirkan lulusan yang tidak kompeten, tidak mandiri, dan akan kesulitan menjalani hidup secara sejahtera.
Penulis juga pernah melakukan observasi di kawasan Pesisir, Kelurahan Panjunan, Kota Cirebon, untuk melihat profil pengangguran di kawasan tersebut. Mayoritas pengangguran yang bisa ditemui, ternyata punya ijazah SLTA. Sebaliknya, banyak pemuda yang putus sekolah, tidak menganggur karena mereka melakukan apapun yang mungkin mereka lakukan untuk mencari penghasilan secara mandiri, entah dengan menjadi buruh pengolahan ikan, nelayan, tukang rongsok, pedagang asongan, dan sebagainya – tanpa terbebani rasa gengsi dan malu. Sementara mereka yang punya ijazah SLTA, cenderung memilih menganggur ketimbang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mereka pandang “hina dan tak layak untuk lulusan SLTA”. Ternyata, pendidikan hingga SLTA yang telah menghabiskan banyak uang, membekaskan mentalitas menak yang salah kaprah – dan bukannya menanamkan kemandirian.
Jika kita melihat data pada skala nasional, kita juga menemukan fakta yang tak kalah memprihatinkan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2007 sarjana yang menganggur jumlahnya empat kali lipat dari tahun sebelumnya, yakni 409.890 orang. Coba kita pikir bersama, apa gunanya kita melahirkan para sarjana yang tentu memakan biaya demikian besar, jika ujungnya mereka menjadi para penganggur. Apalagi, penganggur terdidik acapkali lebih sulit ditangani daripada para penganggur yang masih “polos”. Bahkan kalau mereka berbuat kejahatan, daya rusaknya jauh lebih dahsyat.
Artinya, jika yang dikedepankan adalah ide atau kebijakan perluasan akses pendidikan, seperti melalui penerapan sekolah gratis, kita berada di jalur yang keliru. Sebab, jika kita mengkaji dengan jujur, problem sesungguhnya yang terjadi di dunia pendidikan kita adalah soal mutu, soal efektivitas sistem pendidikan dalam melahirkan pribadi yang mandiri dan produktif. Berapapun uang yang dihabiskan untuk menggratiskan sekolah, itu sama sekali tak akan membantu perubahan, bila output yang dihasilkan tak memiliki karakter mandiri dan produktif. Lebih kongkritnya, dengan mutu pendidikan seperti sekarang, sekalipun semua anak di Kota Cirebon digratiskan sekolahnya hingga SMA bahkan perguruan tinggi, tingkat kesejahteraan maupun struktur perekonomian di Kota Cirebon kemungkinan besar tak akan membaik.
Selain itu, problem yang mendasar di sektor pendidikan kita adalah biaya pendidikan yang tidak rasional. Berbagai komponen pendidikan seperti gedung sekolah, buku dan transportasi anak, cenderung membebani orang tua siswa maupun negara secara berlebihan. Gedung sekolah misalnya, kita bisa saksikan dengan telanjang cenderung tidak efisien, karena kebanyakan hanya dipergunakan pagi sampai siang hari. Tentu akan lebih efisien jika gedung sekolah dipakai secara penuh waktu dan ada kebijakan merger sekolah. Soal buku juga demikian. Jika di masa lalu sebuah keluarga yang memiliki beberapa anak bisa cukup membeli buku sekali untuk kemudian dialihgenerasikan – atau bahkan tak perlu membeli karena buku dipinjamkan oleh sekolah – saat ini setiap semester terpaksa membeli buku. Buku tahun lalu tak bisa dipakai tahun sekarang, demikian seterusnya. Ini jelas penghamburan dana yang keterlaluan. Padahal, apakah ada perubahan signifikan pada isi pelajaran yang ada di dalam buku? Apakah matematika, bahasa Indonesia dan pelajaran lainnya di tahun 2008 berbeda dengan di tahun 2007 dan tahun-tahun sebelumnya? Sejujurnya, yang membuat orang tua murid harus mengeluarkan uang banyak di komponen buku ini adalah sistem ekonomi perbukuan yang tidak rasional. Di balik kebijakan gonta-ganti buku ada jaringan pihak pencari laba yang ingin menjaga status quo di tengah penderitaan orang tua siswa.
Jika inefisiensi semacam di atas tidak dibenahi, peningkatan anggaran pendidikan, penggratisan sekolah dan semacamnya, pada hakikatnya hanya akan menguntungkan segelintir orang. Yaitu mereka yang menjadi muara akhir dari aliran dana itu; mereka yang bisa menimbun asset dari aliran uang negara.
Pendidikan Wirausaha Sebagai Salah Satu Solusi
Ketika kemiskinan dan pengangguran meningkat, ide tentang pendidikan yang berkaitan erat dengan upaya “entrepreneuring society” atau mewirausahakan masyarakat, layak dikemukakan. Kita membutuhkan pendidikan yang bisa mengantarkan masyarakat tumbuh berkembang, menemukan potensi dirinya dan mencapai titik kreativitas tertentu, yang membuat mereka tak terlalu bergantung pada orang lain untuk bisa mencari uang – dan lebih jauh, untuk hidup mandiri secara layak. Praktisnya, kita punya dua pilihan. Pertama, memberi muatan entrepreneurship pada kurikulum pendidikan formal, sehingga kelak akan cukup banyak lulusan sekolah formal yang memiliki kapasitas sebagai entrepreneur. Kedua, memperbanyak lembaga pendidikan entrepeneur yang berorientasi wirausahawan mandiri. Baik yang pertama maupun yang kedua, sejauh berhasil mencetak lulusan yang benar-benar memiliki kapasitas atau kompetensi sebagai entrepreneur, akan menjadi angin segar bagi perekonomian. Setidaknya, pengangguran baru makin sedikit karena akan lebih banyak orang yang sanggup menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Dan lebih jauh dari itu, keberadaan usaha-usaha baru yang diciptakan para entrepeneur made in sekolah formal maupun lembaga pendidikan entrepreneur yang khusus didirikan, akan mendinamisasi perekonomian sekaligus menghadirkan lapangan kerja baru. Efeknya, lapangan kerja baru ini bisa menampung mereka yang memang tak bisa membuka usaha mandiri sehingga jumlah pengangguranpun bisa dikurangi.
Kita bisa membaca hasil kajian Pacific Economi Cooperation Council yang menyatakan bahwa rasio wirausaha berhubungan langsung dengan kemajuan sebuah negara. Negara-negara APEC yang maju memiliki rasio wirausaha yang relatif lebih tinggi. Standarnya adalah, untuk setiap 20 orang penduduk setidaknya terdapat seorang wirausahawan yang bisa mengembangkan usaha kecil dan menengah.
Data menunjukkan bahwa rasio wirausaha di Indonesia adalah 1:83. Itu artinya, di antara 83 orang penduduk, hanya terdapat seorang wirausahawan. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan Filipina yang 1:66. Apalagi dibandingkan dengan Jepang, 1:25, atau Korea Selatan, 1:20
Demikianlah, kita bisa melihat bahwa pendidikan yang berorientasi mewirausahakan masyarakat bisa menjadi jalan yang cukup realistis untuk memecah “kebuntuan hubungan” antara pendidikan dengan peningkatan perekonomian dan penyebarluasan kesejahteraan. Semakin banyak orang yang bisa dididik menjadi wirausaha, semakin banyak sumber daya daerah yang bisa dimanfaatkan, dan semakin berkembang pulalah perekonomian. Dan ini pada akhirnya akan berdampak pada pengurangan pengangguran sekaligus pengurangan angka kemiskinan.
Namun demikian, ada hal yang patut kita cermati ketika kita mengembangkan pendidikan kewirausahaan. Pertama, kita harus paham benar bahwa kewirausahaan bukanlah sekadar soal mendirikan dan mengembangkan bisnis. Kewirausahaan punya makna yang lebih luas. Ia berkaitan pola pikir, pola sikap dan pola bertindak yang berorientasi pada penciptaan nilai lebih dan kemandirian yang bisa diterapkan di seluruh lapangan kehidupan dan berbagai profesi.
Seorang wirausaha adalah sosok yang bisa mempraktekkan prinsip-prinsip kewirausahaan dalam keseharian, mulai dari hal-hal yang mendasar, dalam setiap kesempatan, dan dalam berbagai skala: individu, keluarga, komunitas, daerah. Mendidik wirausaha harus bermula dari menanamkan pola hidup yang berorientasi pada kesejahteraan, yang cirinya adalah mensyukuri segenap karunia dan sumber daya yang dimiliki, selalu berpikir dan bertindak kreatif untuk memberi nilai tambah pada karunia dan sumber daya itu, dan mengutamakan kebersamaan.
Kedua, kita harus memahami bahwa nilai-nilai kewirausahaan terpancar bukan saja dalam kecakapan membaca dan menangkap peluang serta mengkonversinya menjadi sebuah kegiatan penghasil laba, tapi juga dalam kecakapan merasionalisasi pengeluaran dan memenuhi berbagai kebutuhan hidup pada skala individu, keluarga, komunitas dan daerah secara swadaya.
Ketiga, alih-alih menjadi sosok individualis dan egoistis, seorang wirausaha sejak dini harus dididik untuk mengedepankan kebersamaan, menyadari pentingnya jejaring, serta senantiasa terlibat dalam dinamika pembangunan di dalam komunitas dan daerahnya. Karena hanya dengan begitu, seorang wirausaha bisa bermanfaat kepada komunitas dan daerahnya, sekaligus mendapatkan timbal baliknya berupa pasar untuk barang dan jasa yang ia produksi.
Keempat, ketika memasuki kegiatan kewirausahaan yang lebih spesifik, yaitu berbisnis untuk menghasilkan laba, kegiatan bisnis yang dipilih untuk digeluti haruslah yang punya dampak positif terhadap perbaikan neraca ekonomi wilayah dan perbaikan tatanan ekonomi secara umum. Untuk itulah, seorang wirausaha harus mengenal daerah di mana dia akan beraktivitas beserta segenap unsur-unsurnya, mengenal dinamika ekonomi dan mampu menganalisis berbagai dinamika ekonomi itu, dan mampu merumuskan rencana usaha yang inovatif berdasarkan peluang yang dia peroleh setelah melakukan analisis mendalam terhadap realitas daerah.
Jika pendidikan wirausaha hanya dimaknai sebagai kegiatan melatih seseorang agar pintar mencari uang dan cepat meraih kekayaan, hasilnya justru akan kontraproduktif. Alih-alih akan mendekatkan masyarakat pada kehidupan sejahtera, langkah seperti itu malah akan memperburuk tatanan ekonomi daerah dan melanggengkan ketimpangan sosial ekonomi.
Lebih jauh, agar wirausaha yang kita lahirkan melalui proses pendidikan wirausaha bisa memberikan kontribusi bagi penciptaan tatanan masyarakat sejahtera, pada wirausaha tersebut harus diarahkan untuk memiliki tiga kompetensi: mampu mempraktekkan dan meneladankan pola hidup sejahtera, partisipatif dalam pembangunan, serta mampu mengembangkan bisnis mandiri.
Kontekstualisasi Pendidikan Sebagai Solusi Lain
Para pelajar pada saat ini adalah pelaku utama pembangunan di masa depan. Harapan terakhir kita jika kita gagal memperbaiki efektivitas pembangunan di berbagai daerah pada saat ini, terletak pada mereka. Dengan berganti generasi, kita bisa berharap terjadi pula perubahan dan tatanan masyarakat sejahtera benar-benar bisa terwujud.
Namun hal demikian jelas harus dipersiapkan. Jika generasi masa depan tidak lebih baik dari generasi masa kini, atau bahkan lebih buruk, karena pendidikan yang mereka tidak bermutu, impian tentang tatanan masyarakat sejahtera di masa depan tak akan terwujud.
Satu-satunya langkah jitu untuk meningkatkan mutu pendidikan agar para pelajar kita bisa menjadi pelaku pembangunan yang efektif di masa depan, adalah kontekstualisasi pendidikan. Yang dimaksud dengan kontekstualisasi pendidikan, adalah mengkaitkan segenap pelajaran di sekolah dengan kehidupan nyata, khususnya dengan dinamika pembangunan di daerah.
Melalui pendekatan ini, kegiatan pembelajaran di sekolah diposisikan sebagai momen pembelajaran pembangunan, di mana para pelajar belajar tentang hal ihwal daerahnya beserta segenap dinamika pembangunan di dalamnya.
Secara bertahap sesuai tingkatannya, para pelajar difasilitasi untuk menghayati ilmu pembangunan daerah. Pada tingkatan SD, mereka bisa diperkenalkan pada unsur-unsur daerah, sembari mengaitkannya dengan mata pelajaran di sekolah. Unsur-unsur daerah seperti sungai, pepohonan, tanah, air dan udara, bisa dihubungkan dengan pelajaran IPA. Unsur-unsur daerah seperti bangunan perumahan dan perkantoran, taman, jembatan, bisa dihubungkan dengan pelajaran menggambar atau matematika. Demikian seterusnya. Yang pasti, melalui langkah seperti ini para pelajar tingkat SD bisa mengenal daerah di mana mereka tinggal.
Pada pelajar tingkat SMP, kita bisa mengajak mereka mengamati dinamika pembangunan daerah, sehingga berbagai dinamika pembangunan di berbagai sektor: seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, transportasi dan lainnya, mereka kenali. Tentu saja, sebagaimana pada tingkatan SD, kegiatan mengamati berbagai dinamika pembangunan daerah ini bisa dikaitkan dengan seluruh mata pelajaran. Dalam bahasa lain, kita memperkenalkan pembelajaran dengan pendekatan tematik, di mana yang menjadi tema utama adalah berbagai dinamika pembangunan daerah.
Dan pada tingkatan SMA, kita memfasilitasi para pelajar untuk belajar menganalisis berbagai dinamika pembangunan daerah. Mereka dibimbing untuk melihat hubungan sebab akibat antar berbagai peristiwa pembangunan daerah, kaitan antar berbagai sektor, berbagai proses pembangunan dan dampaknya bagi kesejahteraan masyarakat, dan sebagainya. Semua itu dilakukan tentunya tetap dalam bingkai mata pelajaran, tepatnya melalui pendekatan pembelajaran tematik yang mengintegrasikan berbagai mata pelajaran dalam satu tema.
Secara praktis, pembelajaran kontekstual bagi para pelajar sebagaimana terpapar di atas, bisa dilakukan melalui berbagai langkah praktis. Misalnya dengan mengembangkan kegiatan ekstra kurikuler seperti wisata belajar, pembentukan klub peneliti pembangunan daerah, pelatihan jurnalistik dengan obyek tulisan berupa pembangunan daerah dan seterusnya. Bisa juga melalui pengintegrasian materi pembangunan daerah dalam berbagai mata pelajaran, dimulai dengan memasukkan pengetahuan tentang pembangunan daerah ke dalam buku teks. Hal demikian sangat mungkin dilakukan: para aparat dari berbagai SKPD bisa menyumbangkan pengetahuan dan informasi yang mereka miliki untuk diolah oleh guru-guru berbagai mata belajar menjadi teks bahan belajar.
Jika kita mengharapkan anak-anak kita menjadi generasi masa depan yang sejahtera, tampaknya kontekstualisasi pendidikan ini memang sesuatu yang wajib kita lakukan!


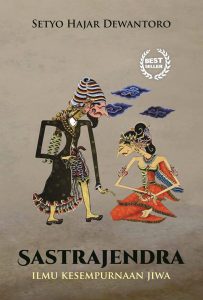
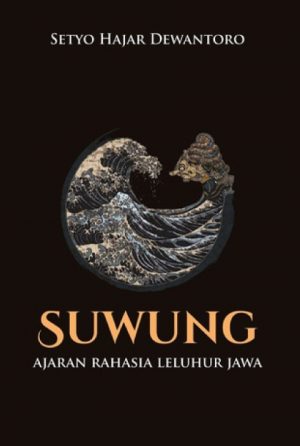

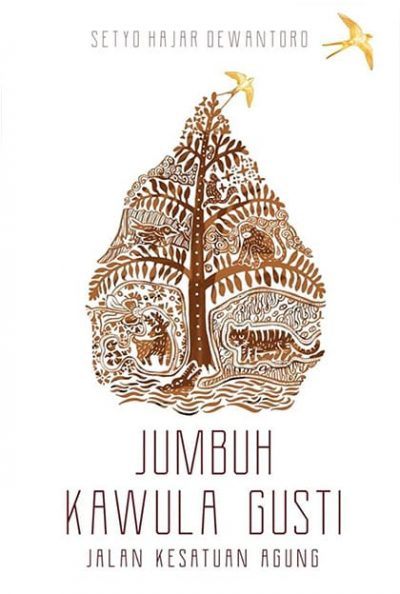
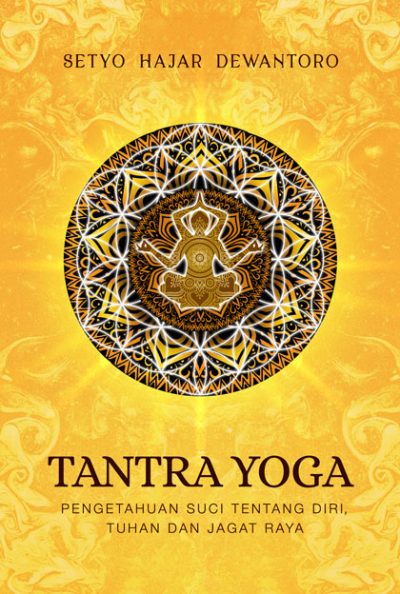
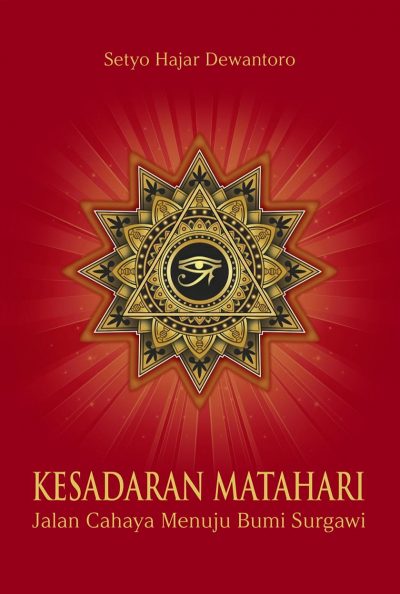









Post a Comment