
Prolog: Potret Muram Kemiskinan di Kota Cirebon
Di bawah rindangnya pohon-pohon Asem di sepanjang jalan utama di Kelurahan Argasunya, setiap harinya ratusan orang berharap-harap cemas menunggu datangnya rezeki. Mereka adalah para buruh Galian C, yang mengantungkan hidup dengan menggali pasir dan batu di sekitar kawasan Kopiluhur. Di salah satu titik dekat kantor kelurahan misalnya, tercatat sekitar 80 orang yang sehari-hari mengantri untuk menaiki truk pengangkut pasir dan batu. Agar mereka mendapatkan nafkah, mereka harus bisa naik ke truk-truk itu. Dan untuk itu, terutama di saat musim penghujan, seorang buruh galian C bisa menunggu semenjak subuh dan baru berangkat ke lokasi galian C pada siang hari, antara pukul 10-12 siang. Mereka harus antri sebanyak 17-20 shift. Semakin jarang mobil truk datang, semakin lama mereka harus mengantri. Tak jarang, menunggu hingga siang hari, seorang buruh galian C harus gigit jari karena tak ada truk yang lewat untuk dirinya.
Pasca pemberlakuan kebijakan resmi seputar penutupan lokasi galian C di Argasunya, seorang buruh galian C akan sangat beruntung jika bisa dua kali terangkut dan mendapatkan upah antara 10.000 – 12.000 rupiah sehari. Sering terjadi, mereka harus bercukup diri dengan 1 kali kesempatan terangkut – itu artinya mendapatkan nafkah 5.000 – 6.000 rupiah.
Kehidupan seperti apa yang bisa diciptakan dengan penghasilan antara 6.000 – 12.000 sehari?
Memang, faktanya tak ada berita tentang buruh galian C ataupun warga Argasunya yang mati kelaparan karena tak punya uang. Tapi, tak perlu kasus seekstrem itu untuk menyadari keberadaan sisi lain dari wajah Kota Cirebon – sebuah sisi gelap, sebuah sudut yang muram. Di tengah fenomena makin banyaknya kalangan kaya yang menghabiskan ratusan ribu rupiah untuk sekali makan di hotel-hotel dan rumah makan berkelas, tentu sebuah ironi menyaksikan keluarga buruh galian C (ataupun warga lain di Argasunya) yang kesulitan untuk secara stabil menyediakan beberapa piring nasi plus tempe goreng dan tumis kangkung. Itu sebuah kemewahan, karena yang paling mungkin disajikan kepada seluruh anggota keluarga dengan penghasilan 6.000-12.000 rupiah sehari adalah nasi putih plus garam, cabai dan terasi, atau secuil ikan asin. Generasi seperti apa yang akan tercipta dari anak-anak yang kekurangan gizi?
Kemuraman di Argasunya tak sebatas pada betapa sulitnya para buruh galian C untuk mendapatkan sekadar 10.000 rupiah sehari. Di ujung Kampung Surapandan yang berbatasan dengan Kampung Cibogo, ternyata masih ada rumah yang tidak dilengkapi sarana listrik. Sang pemilik rumah mengaku, dulu pernah punya sambungan listrik PLN. Tapi karena tidak sanggup membayar, instalasi listrik di rumah itu dicabut dan mereka harus membiasakan diri hidup tanpa listrik.
Anda yang terbiasa ada di gedung terang benderang tapi dingin ber-AC, tentu sulit membayangkan bagaimana rasanya setiap hari hidup di rumah yang gelap tapi panas dan pengap. Untuk membaca, Anda harus menyalakan lampu minyak tanah, atau keluar ruang. Tak ada TV, video apalagi karaoke. Tidak menyenangkan memang. Tapi itulah yang harus dijalani oleh sebuah keluarga di Argasunya, yang sehari-hari berprofesi sebagai petani.
Kemudian, penghuni rumah tersebut – dan beberapa tetangganya, ternyata masih buang aing besar di kebun, karena ketiadaan jamban. Untuk mandipun alakadar, karena air adalah barang mewah di lingkungan bertanah cadas dan tak ada jaringan PAM. Sungguh sulit dihitung, berapa jauh jarak kehidupan semacam ini dengan kehidupan sejahtera.....
Dan masih tentang Argasunya, kepedihan akan mencuat jika kita menyaksikan tanah eks-galian C yang tak pernah direklamasi: lubang-lubang besar yang mengangga. Seperti bekas tanah yang dibom. Dan malangnya, setelah dilingkungi tanah-tanah berlubang tak terawat semacam itu, warga Kopiluhur kini harus berakrab-akrab dengan Tempat Pembuangan Akhir sampah – pindahan dari Grenjeng – yang menebarkan bau menyengat dan mengalirkan limbah cair yang menganggu tanah dan sumur air milik warga.
Sudut Muram di Kesunean dan Cangkol
Di tepian pantai sepanjang Cangkol dan Kesunean, kita bisa menemukan barisan “helikopter”. Tapi jangan salah sangka, ini bukan sebutan untuk pesawat berbaling-baling yang terparkir di sana. Tapi, itu adalah sebutan akrab dari warga setempat untuk tempat buang hajat bersama: sebuah bangunan dari bambu yang menggantung di atas laut! Setiap pagi dan sore, warga antri untuk mempergunakan “helikopter” itu.
Keluarga-keluarga yang terbiasa hidup tertib dan terdidik, bisa jadi menyebut tradisi demikian sebagai tradisi yang “biadab”. Tapi, lepas dari seperti apa nilai moralnya, tradisi mempergunakan “helikopter” adalah sebuah keniscayaan bagi warga miskin di Kesunean dan Cangkol yang belum memiliki jamban sendiri. Soal kesan jorok dan semacamnya, itu sepertinya bukan soal penting ... yang penting adalah kebutuhan manusiawi mereka untuk membuang limbah tubuh setiap hari bisa terpenuhi.
Tapi Cangkol dan Kesunean bukan saja punya “helikopter” yang membuat mereka punya semacam pembeda dengan kawasan lain yang lebih “beradab”. Cangkol dan Kesunean juga adalah kawasan yang luar biasa padat, dengan rumah-rumah yang sempit dan berdempet-dempet, plus gang atau jalan yang cukup dilalui satu orang atau satu sepeda. Hebatnya, warga di kawasan tersebut produktif dalam hal melahirkan generasi baru; bisa dibilang anak-anak kecil adalah asset yang paling bisa dilihat di sana. Mungkin gerakan KB tak pernah sampai ke sana. Dan repotnya, anak-anak kecil di Cangkol dan Kesunean, sejauh observasi penulis, punya problem luar biasa besar: mereka tak punya tempat bermain yang layak – sebuah tempat di mana mereka bisa berlari-lari, bersosialisasi, mengadakan aneka permainan. Jelas kondisi demikian merupakan tragedi: ada sebuah pernyataan yang sangat mengandung kebenaran, “pembunuhan (karakter) terhadap generasi masa depan adalah dengan tidak menyediakan ruang bermain yang layak bagi anak-anak!”
Lebih tragisnya, anak-anak di Cangkol dan Kesunean bukan hanya tak punya tempat bermain yang layak. Mereka juga terpaksa harus merekam berbagai potret kehidupan yang jauh dari sejahtera. Mereka secara sadar maupun tak sadar, langsung maupun tak langsung, menyerap nilai-nilai tertentu dari lingkungan mereka yang jauh dari ideal, baik menyangkut relasi sosial maupun relasi manusia dengan alam dan lingkungan sekitar. Kita bayangkan saja isi benak seorang anak yang setiap hari diisi dengan gambaran tentang orang-orang tua yang berjejal dan berkerumun di berbagai sudut kampung tanpa kegiatan produktif, rumah-rumah yang jauh dari standar kelayakan dengan tata lingkungan yang amburadul, selokan bahkan pantai yang berubah fungsi menjadi sampah, dan berbagai kondisi mengerikan lainnya. Visi pembangunan seperti apa yang akan mereka wujudkan ketika dewasa kelak?
Menyikapi berbagai fenomena penuh kemuraman di atas, perlulah dibuat terobosan. Penulis menawarkan beberapa ide untuk diadopsi oleh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, agar program tersebut benar-benar bisa membantu kaum miskin.
Solusi Pertama: Perbaikan Paradigma
Tolak ukur terhadap keberhasilan pembangunan ekonomi saat ini adalah Indeks Daya Beli. Indeks Daya Beli diukur dari jumlah uang yang dikeluarkan dari sektor rumah tangga ke sektor lainnya, untuk membeli 27 komoditas yang dijadikan faktor pengukuran. Di antaranya adalah beras, bayam, pendidikan, rokok. Semakin besar nilai rupiah yang dikeluarkan oleh masyarakat, maka indeks daya beli akan meningkat dan itu kemudian dimaknai sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakat. Artinya, penggunaan Indeks Daya Beli sebagai ukuran taraf kesejahteraan sama dengan menerapkan logika berikut: “semakin banyak belanja semakin sejahtera”.
Pola produksi subsisten atau swadaya, berdasarkan kerangka daya beli, sama sekali tidak bisa dijadikan komponen pengukuran. Jika seseorang bisa memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya secara swadaya tanpa mengeluarkan uang, misalkan memasak kangkung hasil berkebun sendiri, membangun rumah secara gotong royong tanpa mesti membayar ongkos tukang, dan semacamnya, tak dampaknya sedikitpun pada peningkatan daya beli. Artinya, sekalipun sebuah keluarga bisa memenuhi kebutuhan hidupnya (terutama kebutuhan dasarnya) secara lebih layak, jika itu dilakukan melalui pola produksi subsisten yang menihilkan pengeluaran dana ke sektor lain, taraf kesejahteraannya tak bisa dibilang meningkat, sebab daya belinya juga tidak meningkat.
Padahal, sungguh menyesatkan untuk mengidentikan “banyak belanja” dengan “terpenuhinya kebutuhan hidup”. Pada prakteknya, banyak anggota masyarakat yang telah terdorong berperilaku konsumtif, semakin banyak berbelanja, tetapi taraf kesejahteraannya tidak meningkat. Banyak kebutuhan dasar mereka – kebutuhan gizi, rumah dan lingkungan yang sehat - tidak terpenuhi secara layak. Padahal pengeluaran sehari-hari mereka cukup besar. Mengapa hal demikian terjadi? Sebab mereka membelanjakan uangnya bukan untuk membeli sesuatu yang merupakan kebutuhan dasar, tetapi sekadar keinginan.
Dengan demikian, menyatakan bahwa naiknya point Indeks Daya Beli identik dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat (yang pengertian dasarnya adalah semakin terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat), jelas merupakan sebuah pengaburan persoalan.
Jika kita kaji lebih jauh, penggunaan Indeks Daya Beli sebagai ukuran taraf kesejahteraan, pada akhirnya memuat unsur-unsur pemihakan kepada kepentingan pasar dan pemilik modal. Secara faktual, produk barang dan jasa yang dibeli oleh masyarakat dan kemudian dicatat sebagai komponen Indeks Daya Beli, mayoritasnya diproduksi atau didistribusikan oleh para pemodal besar. Mendorong daya beli masyarakat, artinya mendorong masyarakat makin doyan belanja, makin konsumtif. Dan itu artinya, para pemilik modal yang menjadi muara mengalirnya uang masyarakat, akan kian makmur karena omset dan laba mereka membesar.
Adalah benar, pada beberapa sisi, mendorong daya beli masyarakat memiliki maslahat bagi pertumbuhan sektor riil, termasuk para pelaku usaha mikro dan kecil. Tapi, di tengah tatanan ekonomi daerah yang timpang, mendorong masyarakat kian gemar berbelanja hanya akan memperbesar ketimpangan: memperkaya yang kaya, dan membuat yang miskin jadi kelimpungan (karena tak kuasa menghindar dari jeratan pasar yang selalu menuntut uang dan uang).
Ke depan, perlu dipertimbangkan instrumen pengukuran baru dalam sektor pembangunan ekonomi. Dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri bisa menjadi program awal yang mengadopsi ide perubahan paradigma ini. Dalam hemat penulis, yang paling rasional untuk mengukur apakah sebuah keluarga menjadi lebih sejahtera atau tidak, adalah dengan melihat pertumbuhan asset yang mereka miliki, khususnya tabungan (dalam berbagai bentuk: uang, tanah, hewan ternak, tanaman hias di pekarangan, dll). Sebab, keberadaan tabungan dan penambahan asset menunjukkan adanya selisih positif antara pemasukan dibandingkan pengeluaran yang kemudian terakumulasikan dan termanfaatkan dengan baik.
Jika ukuran ini yang dipergunakan, masyarakat bukannya didorong untuk berbelanja sebanyak-banyaknya (dengan alasan itu akan meningkatkan indeks daya beli), tetapi secara proporsional dibimbing meningkatkan pendapatan sekaligus merasionalkan belanja. Termasuk dalam tindakan merasionalkan belanja, adalah meningkatkan nilai produksi subsisten (upaya produksi barang dan jasa yang dibutuhkan rumah tangga secara swadaya tanpa mengeluarkan uang). Dengan pendekatan ini, masyarakat di satu sisi didorong untuk produktif, di sisi lain didorong untuk hemat dan cermat dalam belanja. Sebab hanya dengan cara itulah mereka bisa meningkatkan nilai asset dan tabungan, yang menjadi ukuran lebih akurat tentang meningkat tidaknya taraf kesejahteraan mereka.
Pemberdayaan Sebagai Solusi Berikutnya
Warga miskin, sejauh ini merupakan korban dari sistem ekonomi yang timpang. Oleh karena itu, akan sangat ideal jika Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri diarahkan untuk menguatkan kapasitas ekonomi kaum miskin; memberdayakan mereka agar punya kesanggupan untuk melampaui jebakan kemiskinan struktural.
Secara umum, penguatan kapasitas ekonomi keluarga miskin harus diarahkan pada dua hal: peningkatan keswadayaan dan rasionalisasi belanja. Selama ini keluarga miskin terperangkap dalam kemiskinannya, bukan saja karena pendapatan mereka rendah, tapi juga karena belanja mereka tidak rasional dan mereka sangat tergantung pada pasar.
Secara praktis, pemberdayaan keluarga miskin harus diawali dengan pembelajaran agar mereka mengenal apa sebenarnya kebutuhan dasar mereka, bagaiman pola pemenuhan kebutuhan itu selama ini, dan apa saja daftar belanja mereka yang sejatinya itu merupakan sekadar keinginan. Berikutnya, mereka diajak mengindentifikasi potensi yang mereka miliki: lahan, keterampilan, jaringan dan semacamnya. Selanjutnya kita harus mendorong mereka berproduksi, terutama yang bersifat subsisten. Ini bertujuan agar semakin tinggi kontribusi produksi subsisten terhadap belanja kebutuhan secara total. Semakin tinggi nilai dan persentase produksi subsisten, akan semakin baik.
Sebagai sebuah ilustrasi, penulis ungkapkan hasil pengamatan di Kampung Surapandan Kelurahan Argasunya Kota Cirebon yang masuk kategori pinggiran atau pedalaman. Kita bisa melihat alasan mengapa mereka bisa bertahan hidup dan dalam beberapa hal lebih layak dibandingkan warga di perkotaan padahal tingkat pendapatan mereka sangat rendah. Salah satu faktor penting yang bisa diungkapkan adalah: mereka masih punya tradisi berproduksi secara swadaya. Memang, secara teori bisa dinyatakan bahwa warga dengan kemampuan produksi swadaya lebih tinggi, cenderung memiliki tingkat kehidupan yang lebih layak.
Salah satu kebutuhan warga Kampung Surapandan yang dipenuhi melalui pola produksi swadaya adalah perumahan. Warga memiliki tradisi arisan material bangunan dan bergotong royong jika ada warga yang berniat membangun rumah, atau ada warga yang benar-benar membutuhkan rumah, misalkan karena rumahnya ambruk. Yang terakhir ini terjadi misalnya, ketika atap rumah Ketua RW Kampung Surapandan ambruk karena lapuk dimakan usia.
Warga yang lain seperti Udin dan Kadirah, bisa membangun rumah tembok kendati penghasilan mereka dulu sebagai buruh galian C – ketika membangun rumah itu – hanya sebesar Rp 20.000 – 25.000 rupiah per hari. Itu mereka lakukan dengan pola arisan material dan gotong royong yang menihilkan komponen ongkos tukang.
Selain itu, beberapa warga melakukan produksi swadaya untuk kebutuhan pangan, untuk komoditas seperti beras, singkong, sayur mayur dan ternak ayam. Dengan pola ini, mereka bisa bertahan hidup sekalipun penghasilan mereka menurun drastis – misalkan ketika kegiatan galian C dilarang.
Pola produksi swadaya ini tampaknya sangat mungkin untuk diterapkan di kawasan lain – termasuk kawasan perkotaan di mana banyak terdapat banyak keluarga miskin. Alih-alih langsung memacu keluarga miskin untuk meningkatkan pendapatan, lebih rasional kalau pertama-tama, membimbing mereka untuk meningkatkan produksi subsisten terlebih dahulu. Toh, dengan asset dan kemampuan terbatas sekalipun, produksi swadaya ini bisa dilakukan.


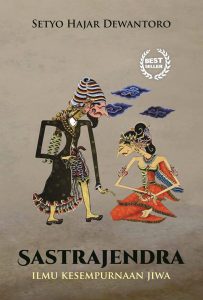
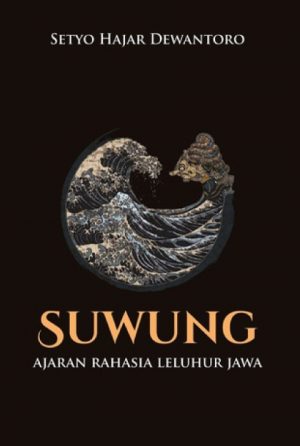

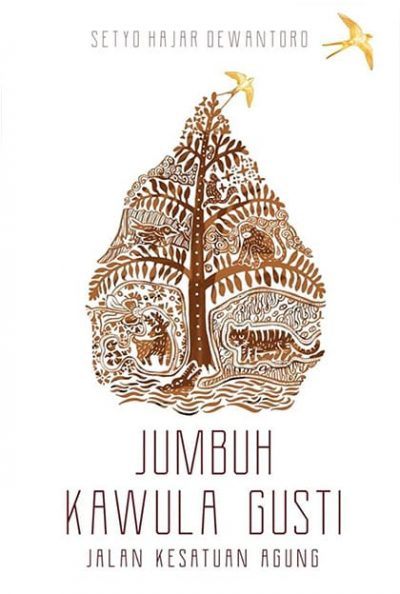
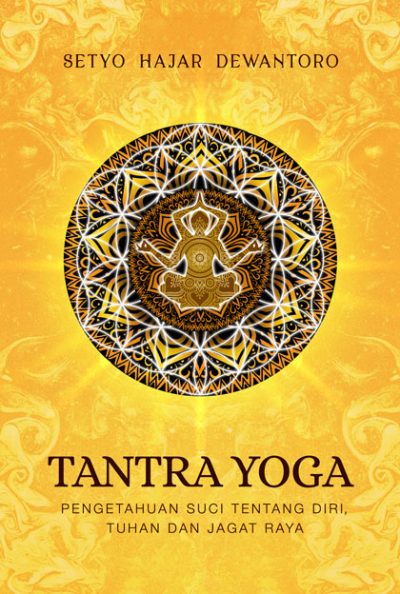
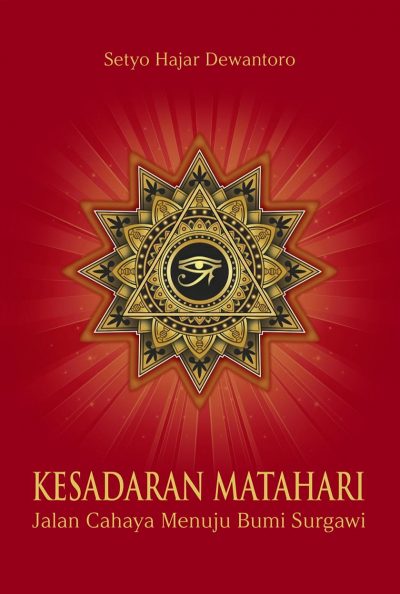









Post a Comment