Purbatisi purbajati, mana mo kadatangan ku musuh ganal musuh alit. Suka kreta tang lor kidul kulon wetan kena kreta rasa. Tan kreta ja lakibi dina urang reya, ja loba di sanghiyang siksa.
Apabila ajaran dari leluhur dijunjung tinggi, tidak akan kedatangan musuh, baik berupa laskar maupun penyakit bathin. Senang sejahtera di utara, barat, dan timur. Yang tidak merasa sejahtera hanyalah rumah tangga orang banyak yang serakah akan ajaran agama.
(Prabu Siliwangi)
Sebuah pertanyaan menggelitik benak, “Mengapa para leluhur saya dulu ada yang mengganti agama begitu bersentuhan dengan kaum pendatang? Ketika bersentuhan dengan bangsa India, para leluhur menjadi pemeluk Hindu dan Budha, ketika berhubungan dengan orang Arab, Parsi, ataupun juga orang Cina dan India (yang telah memeluk Islam), merekapun menjadi Muslim. Apakah mereka percaya bahwa agama-agama yang baru itu lebih membawa keselamatan ketimbang agama lama yang mereka anut?”
Merenungkan beberapa teks sejarah yang bisa saya baca, sedikit jawaban mulai terkuak. Perpindahan agama di Pulau Jawa, secara umum berlangsung damai, dan itu biasanya dimulai dari perpindahan agama pada kalangan raja dan penguasa. Ketika seorang raja atau penguasa berpindah agama atau mengadopsi keyakinan baru, bisa dipastikan kebanyakan rakyat mengikutinya. Itu yang menjawab mengapa nyaris tidak ada perang agama di Pulau Jawa, baik di masa kedatangan Hindu, Budha dan Islam.
Sejarawan Barat seperti Vlekke dan Ricklefs, menganalisis bahwa salah satu cara pandang raja-raja Jawa adalah bahwa kekuasaan itu selalu berpangkal pada kekuatan spiritual. Jika seseorang bisa mengakumulasi kekuatan bathin yang itu diraih melalui jalan agama (melalui laku tapa, laku prihatin sebagaimana diajarkan agama), maka kekuasaanpun bisa diraih bahkan dilanggengkan. Mereka juga meyakini bahwa kesejahteraan daerah kekuasaan bisa diraih jika mendapatkan topangan kekuatan langit.
Ketika raja-raja Tanah Jawa bersentuhan dengan peradaban asing, dan mereka menyaksikan keunggulan peradaban tersebut, paradigma mereka mengarahkan pada kesimpulan bahwa itu pastilah terkait dengan keunggulan spiritual. Dan keunggulan spiritual itu, tentu saja berkaitan dengan agama. Maka, untuk memperkuat posisi kekuasaan mereka, memeluk agama baru merupakan sebuah pilihan yang logis. Dengan agama baru itu, para raja dan penguasa di Tanah Jawa berharap bisa mentransfer kekuatan spiritual yang dimiliki para penguasa di tanah nun jauh di seberang. Dengan begitu bisa membangun kekuatan yang lebih hebat untuk kepentingan melanggengkan kekuasaan maupun mensejahterakan rakyat.
Vlekke misalnya memaparkan:
“ Orang Indonesia mungkin juga berperan aktif dan berlayar ke India dengan inisiatif sendiri. Orang-orang ini, yang pada jaman tersebut atau setelah itu berlajar ke Madagaskar yang jauh dan tetap terkenal sebagai pelaut ulung sepanjang sejarah mereka, pastilah tidak kesulitan dalam melayarkan kapal mereka dari Sumatra ke Benggala atau pantai Coromandel.
Kontak dengan India membuat orang Indonesia menyadari pencapaian budaya Hindu. Pemahaman yang meningkat akan status raja-raja India yang lebih berkuasa membangkitkan keinginan untuk menyamainya. Dalam konsep, pemahaman mereka akan benda, kepemimpinan manusia, dan kekuatan gaib berkaitan erat. Kalau mereka menginginkan status superior raja-raja India, mereka harus memperoleh ilmu gaib yang menjadi sumber kekuatan gaib para raja itu. Jadi, mereka meminta para pedagang India bukan hanya barang-barang materi tetapi, terutama, pemimpin-pemimpin spiritual. Akibatnya, para Brahmana datang berkunjung ke kepala suku lokal atau regional di sepanjang pantai Asia Tenggara, dan merekalah yang mendirikan monumen-monumen pertama dengan gaya India dan mengarang prasasti-prasasti pertama dalam bahasa Sanskerta yang awalnya asing, yang ditempatkan di pantai Sulawesi atau Kalimantan, tak kalah asingnya dengan prasasti Latin kontemporer di pantai-pantai bersapu angin di Laut Utara.”
Lebih jauh Velke menjelaskan:
“ Selama berabad-abad, raja-raja Jawa terbiasa memanfaatkan praktik keagamaan sebagai cara untuk meningkatkan tenaga dalam atau kekuatan gaib mereka. Bisa dimengerti kalau mereka memandang Islam dengan cara yang sama. Peningkatan pengaruh agama baru itu di seluruh Asia Tenggara membuktikan kesaktiannya. Mengapa penguasa-penguasa Jawa tidak menerima Islam juga? Mengapa mereka tidak menambahkan sumber baru kekuatan gaib ini kepada sumber yang sudah mereka kenal? Ada dua manfaat yang bisa mereka peroleh sekaligus: mereka akan sejajar secara spiritual dengan kaum Muslim yang mungkin akan menjadi musuh mereka, dan mereka mungkin bisa memperoleh bantuan dari kaum Muslim ini untuk melawan musuh-musuh non-Muslim mereka.”
Dengan paradigma seperti itu, maka bisa sangat dipahami pula jika yang kemudian dilakukan adalah semacam “pengayaan” agama, atau dalam bahasa yang agak peyoratif: sinkretisme. Para raja dan penguasa di Tanah Jawa, berpindah agama bukan berarti meninggalkan agama lama dengan sepenuhnya. Tapi, yang mereka lakukan adalah mempertahankan unsur-unsur agama lama sembari menambahkan unsur-unsur agama baru. Maka, ketika bertemu Hindu dan Budha, mereka memeluknya tanpa kehilangan tradisi Kejawen mereka. Demikian pula, saat memeluk Islam, tradisi Kejawen beserta Hindu dan Budha tidaklah hilang.
Dari perspektif yang lain, apa yang dilakukan oleh para raja dan penguasa Tanah Jawa, merupakan sebuah langkah cerdas yang meminjam bahasa budayawan Umar Kayam disebut dengan “dialog kreatif”. Dialog kreatif dapat dimaknai sebagai, “Menyerap nilai-nilai luhur dan unggul dari tradisi asing, kemudian menyerap dan menggabungkannya ke dalam tradisi lokal”
Proses ini bisa terlihat dengan sangat jelas salah satu karya budaya Nusantara, wayang. Pada masa Hindu-Budha, cerita-cerita klasik seperti Mahabarata dan Ramayana yang menjadi rujukan para penulis dan dalang Nusantara, diadaptasi sedemikian rupa sehingga menjadi sangat khas Nusantara. Misalnya adalah dengan penambahan karakter-karakter baru yang benar-benar mencerminkan kearifan lokal: Semar dan anak-anaknya yang menjadi punakawan, Petruk, Gareng, Bagong. Saat Islam masuk ke Nusantara, pola demikian kembali terjadi. Dengan dimotori Sunan Kalijaga misalnya, wayang yang pada awalnya bernafaskan Hindu-Budha dipergunakan sebagai medium dakwah dan tetap menjadi kesenian yang populer bagi berbagai lapisan rakyat, setelah diadaptasi dan diberi nafas Islam.
Proses ini menggambarkan proses dua arah: di satu sisi kebudayaan lokal Nusantara dipengaruhi oleh kebudayaan asing, yaitu Hindu, Budha dan Islam, dan pada sisi lain, terjadi proses pelokalan atau peng-Indonesia-an Hindu, Budha dan Islam. Dialog kreatif ini menjadikan tradisi dan kebudayaan asing yang dipandang lebih maju, memberikan manfaat bagi pertumbuhkembangan dan transformasi budaya lokal, karena ketika diterapkan, telah dibuat menjadi selaras dengan alam berpikir manusia Nusantara, dan tentunya, juga dibuat selaras dengan tantangan dan problematika lokal. Dalam bahasa lain, nilai-nilai luhur dari tradisi dan kebudayaan asing diserap, tetapi nilai-nilai luhur dari kebudayaan lokal tetap dipertahankan. Sintesa kebudayaan asing dan kebudayaan lokal inilah yang menciptakan sebuah bangunan kebudayaan baru yang kukuh: yang kemudian menjadi basis kejayaan pada ranah ekonomi dan politik.
Sayang sekali, pola dialog kreatif ini tak berjalan mulus pada masa kedatangan Islam. Ketika berhadapan dengan Islam, para penguasa dan rakyat Nusantara tidak begitu berhasil melakukan dialog kreatif. Pelokalan atau peng-Indonesia-an Islam yang menjadi ciri dari upaya dialog kreatif, pada prakteknya harus berhadapan dengan arus “pemurnian Islam”. Kita mencatat, bahwa di luar pergulatan kekuasaan yang semata-mata didasari motif berebut kekuasaan dan materi antar penguasa lokal, pergulatan teologis antara kelompok yang memiliki kecenderungan meng-Indonesia-kan Islam (yang kemudian distigma sebagai kaum abangan) dan yang memiliki kecenderungan meng-Islam-kan (baca: meng-Arab-kan) Indonesia – dikenal sebagai kaum santri juga terjadi. Sejarah membuktikan bahwa secara umum, gerakan pemurnianlah yang menang – disimbolkan dengan penghukuman terhadap tokoh sinkretik seperti Syeikh Siti Jenar, Syeik Mutamakkin, lainnya. Ini salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat Nusantara kehilangan jatidirinya (seperti orang Jawa yang tidak menjadi Jawa lagi karena sepenuhnya terserap dalam budaya Arab).
DI samping mengakibatkan semacam alienasi budaya dan keterkikisan jatidiri bangsa, pergulatan yang berlangsung panjang itu juga jelas sangat menguras energi; hingga pada titik menciptakan kelemahan sekaligus keterbelahan antar kelompok yang tentu saja memudahkan kolonialis yang hendak menaklukkan Nusantara. Ketika dua kelompok ini bersaing bahkan berkonflik, VOC atau Pemerintah Hindia Belanda misalnya, tinggal memihak dan memenangkan salah satu pihak untuk kemudian meminta kompensasi yang makin mengukuhkan kekuasaan mereka.
Hingga saat ini, pergulatan semacam ini – yang tampaknya cenderung dimenangkan arus pemurnian Islam - terus terjadi, dan hasilnya adalah alienasi budaya dan keterkikisan jatidiri di satu sisi, dan di sisi lain adalah perpecahan antar komponen bangsa yang berbeda pendekatan dalam menafsirkan Islam. Dan patut ditengarai, ini berperan melanggengkan kemunduran kita sebagai sebuah bangsa.
Bagaimana menurut Anda?
Subscribe to:
Post Comments (Atom)


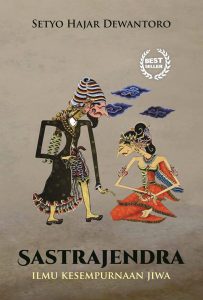
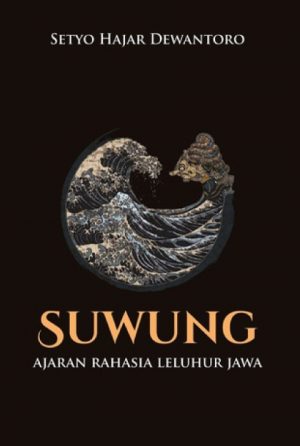

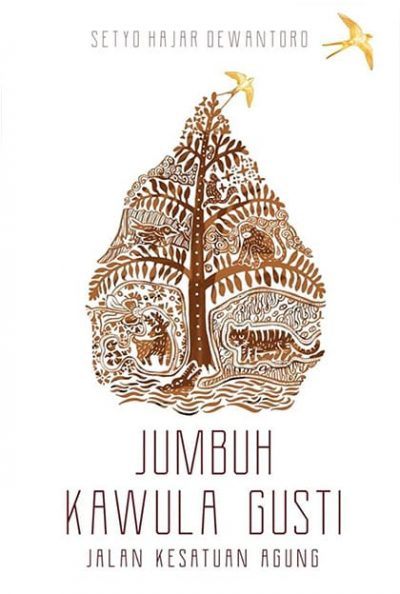
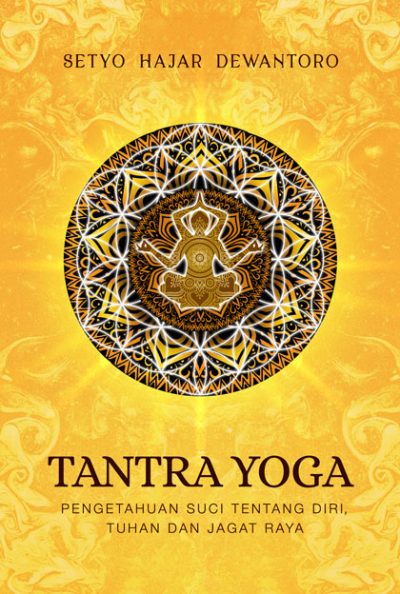
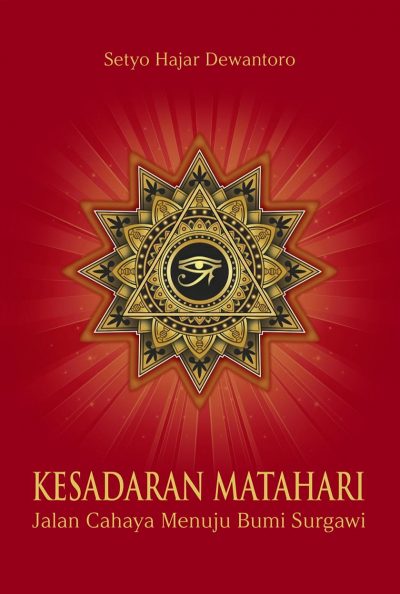









Post a Comment