Sudah sebulan lebih saya tidak menulis tentang perjalanan
menemukan tirta perwitasari. Bukan tidak
ingin menulis. Tapi, entah mengapa,
kemampuan mengalirkan kata-kata seolah lenyap.
Ide dan gairah kuat untuk menulis entah bersembunyi di mana. Padahal, sebulan terakhir ini, saya sering
sekali melakukan tirtayatra atau perjalanan spiritual ke berbagai tempat. Ibarat koki, sebetulnya saya sudah kulakan
cukup banyak bahan. Tapi, saya
kehilangan “mood” untuk meraciknya, sehingga bahan-bahan itu diam teronggok.
Puji syukur kepada Gusti Ingkang Murbeng Dumadi...sepulang
dari perjalanan terakhir ke berbagai petilasan di sekitar Solo bersama Mas Dipa
dan teman-teman, gairah dan daya untuk menulis ini kembali hadir. Di Solo, saya memang sembat ngobrol dengan
Mas Dipa, tentang mengapa belakangan ini kreativitas dalam menulis kok bisa
mandeg. Obrolan itu yang bisa mengurai
akar masalahnya ada di mana. Salah
satunya, beberapa waktu belakangan, tanpa sadar saya mengubah gaya menulis
saya. Dalam beberapa tulisan terakhir, saya
cenderung berpikir mencari ide terlebih dahulu, meninggalkan “kebiasaan” lama
dalam menulis: menceritakan pengalaman,
dan membiarkan ide muncul dengan sendirinya seiring dengan alur pengalaman
itu. Karena saya ngotot mencari sang
ide, dia malah bersembunyi..barangkali takut ya......he, he, he....
Baiklah para pembaca....saya ingin bercerita perlahan-lahan,
setahap demi setahap, karena sebagai hasil perjalanan dan ngangsu kawruh sebulan belakangan ini, banyak sekali yang ingin dan
bisa saya ceritakan......
Pelajaran Selama Menuju
Munggur
Awal bulan Juli 2012, saya kembali berkunjung ke Munggur,
sebuah desa di Kabupaten Karanganyar.
Ada satu proses pembelajaran bersama Mas Dipa dan teman-teman
seperguruan, yang akan dilaksanakan di desa itu, tepatnya di Sendang Gantung,
sebuah sendang panglukatan yang baru saja kembali ditemukan. Saya berangkat dari rumah sudah tengah hari,
karena harus melaksanakan kewajiban saya sebagai seorang ayah, mengantarkan
anak untuk tes masuk sekolah. Pukul 20.00,
ternyata saya baru tiba Semarang. Saya
hampir putus asa dengan nyaris membatalkan kedatangan ke Mungur, karena
sebelumnya mendapatkan info bahwa pembelajaran akan dimulai paling lambat pukul
21.00. Jika saya jam 20.00 masih ada di
Semarang, paling cepat, jam 24.00 baru bisa sampai Munggur. Tapi, setelah ada konfirmasi bahwa kedatangan
saya ditunggu sampai jam berapapun, saya bulatkan tekad untuk melanjutkan
perjalanan.
Memang, untuk bisa ngangsu
kawruh dengan baik itu banyak tantangannya.
Dan demikianlah rumus semesta: tidak ada hal istimewa yang bisa diraih
asal-asalan atau dengan cara yang mudah.
Sesuatu yang istimewa hanya bisa diraih melalui perjuangan keras dan
disiplin tingkat tinggi, plus tekad sekuat baja. Kaweruh yang saya coba pelajari dari Mas
Dipa, adalah kaweruh yang memberi hasil nyata: meminjam bahasa KGPAA
Mangkunegoro IV, itu adalah sugih ngelmu,
sugih bondo, sugih kuwoso. Dalam
bahasa lain, saya tengah belajar tentang kaweruh
Jawa yang memberikan jaminan seseorang bisa memperoleh mencapai tataran nimpuno dan memperoleh kamukten. Siapapun yang telah tuntas mempelajari kaweruh ini - seperti ditunjukkan oleh
kehidupan guru saya, bisa mendapatkan berbagai hal yang dirindukan oleh setiap
manusia: kehidupan rumah tangga yang ayem tentrem, keberlimbahan finansial,
kebahagiaan karena bisa menolong banyak orang, budi pekerti yang luhur, bahkan
juga kekuatan ala Upasara Wulung, sang pendekar linuwih dalam novel Senopati Pamungkas
karya Arswendo Atmowiloto.
Nah....untuk belajar kaweruh
yang berharga hingga tuntas, jelas kita harus berkorban, siap menanggung derita
tertentu selama belajar. Sebagai
ilustrasi, hampir setiap minggu saya menempuh perjalanan menggunakan bis dari
Kuningan ke Solo selama 10-12 jam untuk bisa belajar dari Mas Dipa. Jika pas saya ada pekerjaan di Jakarta, dan ada jadwal belajar, tentu jarak
tempuh menjadi bertambah. Tapi, selama kita memang sungguh-sungguh mau
berhasil, selalu ada jalan. Dan pasti
juga berlaku rumus: “Tak ada tantangan
yang tak bisa ditaklukkan, tak ada kesulitan yang tak bisa dipecahkan”. DENGAN TEKAD KUAT DAN KETULUSAN, KITA PASTI
BERHASIL DALAM BELAJAR.
Kembali ke perjalanan menuju Munggur. Saya tiba di Terminal Tirtonadi pukul
00.30. Tengah malam demikian, sudah
tidak ada bis menuju Munggur. Maka saya
menumpang bis tujuan Surabaya, lalu turun di Masaran, Sragen. Dari situ, saya menumpang ojeg. Pas kebetulan, penarik ojeg yang ada saat
itu, adalah orang Sunda, dari Tasikmalaya.
Maka, setelah awalnya berkomunikasi menggunakan Bahasa Jawa, beralih
memakai Bahasa Sunda.
Dari Pak Juju, sang penarik ojeg itu, saya bisa belajar
tentang “kehidupan”. Ia menarik ojeg
malam hari, dan di pagi hari menjadi tukang kunci, mangkal di Pasar Masaran. Dengan cara demikian, ia bisa mendapatkan
penghasilan untuk bertahan hidup. Saya
salut dengan semangat dan kesabarannya untuk menanti datangnya rupiah demi
rupiah. Menjadi tukang ojeg, juga tukang
kunci, adalah profesi yang benar-benar harus mengandalkan kesabaran: kita harus
benar-benar sabar menanti konsumen datang.
Di saat paceklik, bisa saja tak ada satu konsumen datang. Tak terbayangkan jika saya harus menjalani
profesi tersebut......Tapi, saya belajar bahwa untuk bertahan hidup, banyak
jalan bisa diambil. Dan selama seseorang
bisa menggabungkan kesabaran, ketekunan, dan kerja keras, dia pasti bisa
bertahan. Apalagi jika ditambah
kecerdasan dan strategi yang canggih, keberhasilan adalah hal yang niscaya
diraih.
Sendang Gantung
Saya tiba di Munggur, tempat Mas
Dipa membabarkan kawruh kepada teman-teman seperguruan, jam 01.30. Sayapun langsung duduk menyimak. Tak lama setelah itu, Mas Dipa mengajak kami
ke Sendang Gantung yang ada di desa tersebut.
Sendang Gantung ini menunjukkan jenis dari sendang tersebut, yang
posisinya menggantung, di lereng sebuah sungai.
Di dekatnya, ada dua pohon besar dan berumur tua yang menaungi. Di beberapa titik, bebatuan menjadi ornamen penambah
kharisma sendang itu.
Mengenai sendang, dalam kawruh Jawa, ternyata dikenal
beberapa jenis sendang. Ada sendang yang
khusus untuk diambil tirtanya, untuk kebutuhan upacara keagamaan. Ada sendang yang khusus untuk panglukatan,
yaitu menghilangkan energi negatif dan menyembuhkan penyakit seperti santet,
gila, dan semacamnya. Ada pula, sendang
kenyo/joko yang digunakan untuk memandikan pemuda/pemudi di acara
perkawinan. Sendang Gantung, adalah
sendang dengan fungsi panglukatan.
Tiba di Sendang Gantung, kami bersiap-siap untuk menjalankan
prosesi manembah dan manekung di situ.
Tindakan pertama yang dilaksanakan adalah menyiapkan banten atau
uborampe/sesaji, berupa pisang raja, bunga tiga warna yaitu bunga mawar merah,
bunga mawar putih, kenanga, juga sesari berupa uang, dan minyak wangi. Sesaji itu ditata sedemikian rupa: pisang
raja berada di tengah, lalu bunga mawar merah, mawar putih, dan kenanga,
diletakkan di atasnya, dengan susunan yang rapi mencerminkan pancer dan 4
penjuru mata angin. Setelah struktur
utama sesaji terbentuk, baru di semua tempat di nampan sesaji, ditaburi bunga
tiga warna juga.
Setelah itu, disiapkan dupa wangi. Dupa wangi yang telah tersulut, dipasang oleh
Mas Dipa di beberapa tempat yang dinilai memiliki “energi” tertentu, atau
ditempati entitas metafisik tertentu.
Proses menancapkan dupa-dupa ini dilakukan dengan berputar berlawanan
arah jarum jam, sebagai simbol menjemput anugerah. Pusat energi berada di lokasi di mana pohon
besar dan batu hitam berada. Tetapi, di
tempat-tempat sekelilingnya juga terdapat simpul energi lain yang lebih kecil
intensitasnya. Jika dibuat analogi,
istana utama ada di pusat, di sekelilingnya terdapat bangunan-bangunan
penunjang.
Setelah sesaji siap dan dupa terpasang, kami semua duduk dan
menyiapkan diri untuk memasuki alam keheningan.
Mas Dipa lalu mengucapkan mantra-mantra pengantar: berupa penghaturan
sembah bakti kepada Gusti Hyang Widhi dan manifestasinya: Sang Hyang Purwa,
Madya, Wasana, kepada Bapa Angkasa, Ibu Pertiwi, sedulut papat kalima pancer,
kepada para leluhur, kepada para padanyangan dan penguasa kekuatan jagad,
khususnya yang bersemayang di Sendang Dawe.
Selain berisi penghaturan sembah bakti, mantra itu juga menegaskan
maksud kehadiran ke Sendang Gantung, dan penyerahan sesaji dan permohonan agar
sesaji diterima, sekaligus menyatakan maaf jika sesaji tersebut kurang patut.
Tuntas mantra pembuka, bumi atau pertiwi ditepuk tiga
kali. Dilanjutkan dengan pembacaan doa
oleh Pak Puja, dan sessi meditasi oleh masing-masing. Dalam meditasi tersebut, kami melakukan
meditasi pertiwi dan meditasi angkasa untuk menyatukan diri dengan jagad ageng
yang terepresentasikan oleh Sendang Gantung dan entitas metafisik yang ada di
sana, sekaligus menyerap energi positif yang ada. Pola meditasi demikian, kami lakukan, sesuai
dengan konsep “nyawijiaken jagad alit lan jagad ageng”. Secara lebih jelas, kami yang ngangsu kawruh
dari Mas Dipa dibimbing untuk membangkitkan kekuatan yang ada di dalam diri,
sekaligus menyerap energi semesta. Karena
seseorang bisa memiliki kekuatan dahsyat jika kekuatan di dalam dirinya bangkit
melalui olah nafas, lalu mendapatkan dukungan semesta dengan segala unsurnya:
leluhur, padanyangan, betara-betari, yang masing-masing memiliki energi dan
siap nyengkuyungi kita dengan energi itu.
Setelah meditasi pertiwi dan meditasi angkasa, saya sendiri
melakukan manekung dengan orientasi memasrahkan diri kepada Tuhan Yang
Mahasuci, mencapai hening dan rasa menyatu dengan semesta. Meditasi diselimuti gelapnya malam, di tengah
semerbak wangi dupa, di lokasi dengan aura mistis yang kuat, jelas memberi
sensasi tersendiri. Damai, rasa dingin
yang berpadu dengan kehangatan, benar-benar membawa kenikmatan spiritual. Yah, kenikmatan spiritual ini adalah ganjaran
langsung untuk tekad kuat melaksanakan tirtayatra!
Setelah prosesi manembah, bergantian kami mandi di sendang
tersebut, dengan niat melukat seluruh energi negatif dan keburukan di dalam
diri. Byurrr....nyesss...air dingin yang menyejukkan menyirami badan kami. Dan yang merasa sejuk bukan saja raga, tapi
juga sang sukma. Ya...mandi di Sendang
Gantung, saat fajar akan merekah, menambah sensasi saat meditasi. Damai, hening, segar..demikian yang saya
rasakan.
Cerita tentang Candi
Dukuh dan Sendang Lanji
Setelah acara di Sendang Gantung, saat fajar merekah, saya
melanjutkan perjalanan. Saya punya janji
bertemu dengan Mas Bayu Budi, sederek yang dulu juga menemani saya tirtayatra
ke Candi Gedong Songo. Saya dan Mas
Bayu Budi bertemu di Ungaran. Dari situ,
menggunakan kendaraan Mas Bayu Budi, kami meluncur menuju Candi Dukuh yang
berada di sisi Rawa Pening, tepatnya di Desa Rowo Boni. Tapi, kami tidak melakukan proses manembah
dan manekung di situ. Kami hanya
melihat-lihat. Kebetulan, candi tersebut
sedang direnovasi.
Candi Dukuh, terbuat dari bahan batu andhesit berwarna
hitam. Saya lalu bertanya kepada Mas
Dipa tentang kategorisasi berdasarkan sastra/ajaran Jawa yang tertera dalam
lontar kuno, dan Candi Dukuh ini tergolong candi jenis mana. Saya mendapatkan paparan, bahwa candi itu
terbagi menjadi tiga kategori, yaitu candi untuk perabuan – kebanyakan candi di
Jawa Timur kebanyakan adalah candi jenis ini; lalu candi untuk proses ritual –
Candi Gedong Songo adalah salah satu contohnya; dan candi pertapaan untuk mendadar
diri. Di sekitar Candi Gedong Songo yang
menjadi pusat percandian di sekitar Gunung Ungaran, terdapat beberapa candi di
sekelilingnya dengan fungsi masing-masing.
Candi Arjuna di Dieng, termasuk candi yang mengelilingi Candi Gedong
Songo, dengan fungsi sebagai candi pertapaan untuk pendadaran para brahmana. Sementara Candi Dukuh adalah candi pertapaan
untuk mendadar para satria. Biasanya, di candi pertapaan seperti ini, ada
bangunan dari batu berbentuk altar rata yang menjadi tempat duduk samadhi.
Dari sisi ilmu arkeologi, dengan bahan batu andesit hitam,
Candi Dukuh, sebagaimana Candi Gedong Songo, diperkirakan dibangun sebelum masa
Majapahit. Terlebih, baru-baru ini
petugas Balai Pelestarian dan Peninggalan Purbakala (BP3) Jawa Tengah telah
menemukan tujuh lempengan emas yang diduga berasal dari abad ke-9 Masehi. Di
setiap lempengan emas berbentuk pipih itu terdapat simbol-simbol Hindu. Itu menunjukkan pendirian Candi Dukuh juga
pada abad 9 Masehi.
Setelah puas melihat-lihat Candi Dukuh, saya dan Mas Bayu
Budi, melanjutkan perjalanan. Ndilalah kok
Mas Dipa mengajak bertemu di Sendang Lanji.
Maka, dari Rawapening, kamipun meluncur ke Sendang Lanji di Miri,
Sragen. Menyusuri jalur
Salatiga-Sragen,melewati Gemolong, kami coba menemukan Sendang Miri. Kami bertanya-tanya ke sana kemari sebelum
akhirnya bertemu sendang tersebut. Saya
memang sudah beberapa kali ke situ, tapi karena tidak terlalu memperhatikan
jalannya, jadi agak lupa lokasi.
Di Sendang Lanji, kami bertemu Mas Dipa dan Pak Puja. Setelah ngobrol beberapa saat, kami mulai bersiap
melaksanakan prosesi manembah. Setelah
menyiapkan sesaji, menyulut dupa, kami duduk bersila. Mas Dipa membaca mantra pengantar, Pak Puja
membaca doa, dan kamipun bersemedi. Saat
Mas Dipa mulai membaca mantram, dan kami masuk pada keheningan, terjadi
fenomena alam yang menarik.
Tiba-tiba,
hadir angin mendesau-desau. Saat yang
sama, sapi-sapi yang ditambatkan di kandang di dekat sendang, ikut meramaikan
suasana dengan lenguhannya. Dan fenomena
seperti ini, menunjukkan kehadiran dan keberadaan entitas spiritual yang
jumeneng di Sendang Lanji.
Seperti pernah saya tuliskan di bagian terdahulu, Sendang
Lanji adalah petilasan Ratu Shima, tokoh ratu yang bijaksana, bertahta di abad
7 Masehi. Leluhur yang telah
bertransformasi menjadi entitas cahaya, saat anak keturunannya melakukan proses
manembah, biasanya hadir dengan menunganggi kekuatan alam seperti angin. Kehadiran leluhur, justru bisa dirasakan oleh
binatang yang lebih peka karena hidupnya selaras dengan ritme semesta. Karenanya, saat-saat prosesi manembah
dilakukan, binatang seperti sapi ikut-ikutan ramai dengan lenguhannya..itu
simbol penyambutan mereka atas kehadiran entitas spiritual.
Sungguh, saya sangat menikmati saat-saat seperti ini..hanyut
dalam keheningan, lalu tenggelam dalam fenomena alam yang penuh misteri, dan
merasakan terpaan energi yang lembut mendamaikan.
Demikian yang bisa saya sampaikan pada bagian ini, semoga
bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan
lain, dengan cerita yang berbeda.......




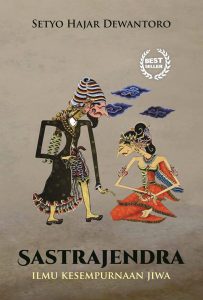
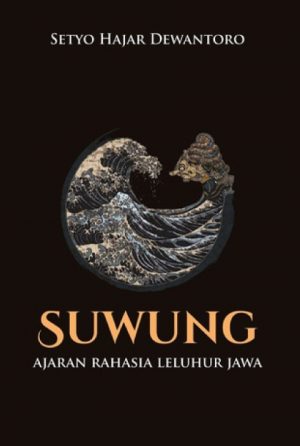

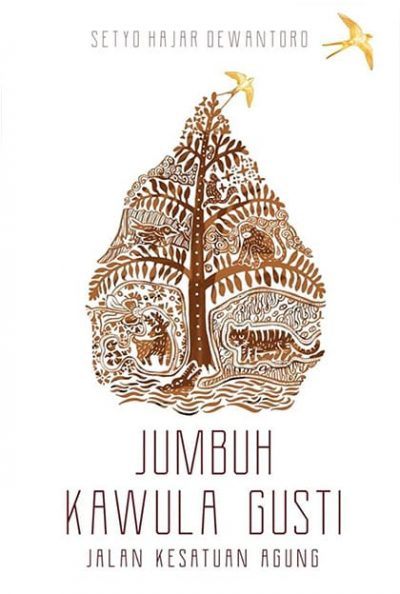
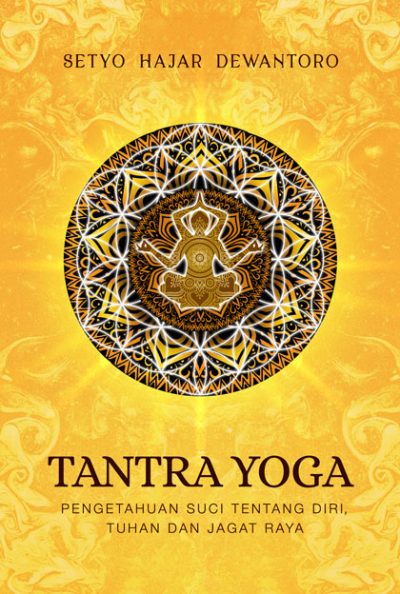
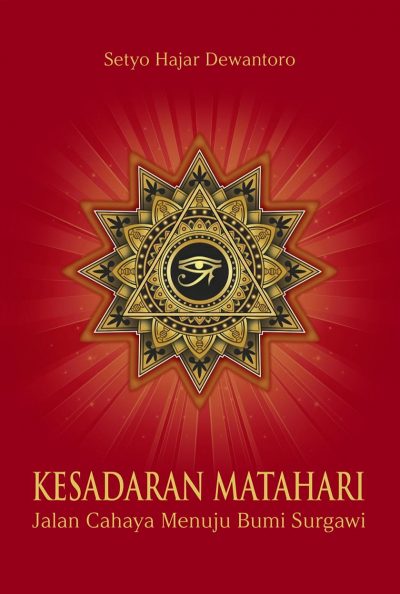









Post a Comment